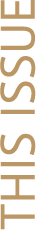Dua Hari Penuh Arti Menjelajahi Istanbul Turki

Pendaratan pagi hari di Istanbul, mempertemukan dewi dengan bandara Ataturk yang seolah masih mengumpulkan nyawa setelah istirahat malam. Tenang, hening, dan lengang. Di merayakan tahun baru 2017, Istanbul sempat menjadi sasaran teror, yang membuat sebagian orang merasa, destinasi ini terlalu beresiko. Namun kota budaya di Turki tetap berjalan dengan semestinya, stabilitas kota terjaga dengan baik dan dewi merasa aman berada di sini.
Hari masih gelap saat bus kami yang dilengkapi wifi melintas. Kesibukan warga Istanbul rupanya sudah dimulai. Kami turun di sebuah hotel tak jauh dari bandara untuk sarapan. Hari belum juga terang. Menu makan pagi Turki yang lengkap tersedia di buffet. Kami memilih menikmatinya di teras berdinding kaca. Semangkuk sup mi mengingatkan akan sup alfabet dari masa kecil yang gurih namun ringan, cocok sebagai pembuka. Piring ke-dua berjodoh dengan börek, lapisan kulit pastry dan keju yang masih hangat, sucuk (sosis khas Turki), keju lokal, dan potongan paprika serta jamur dengan saus tomat. Kami menghabiskannya sementara langit Istanbul tampak berangsur-angsur terang di balik dinding kaca.
Pagi hari di kota pusat budaya Turki ditandai dengan munculnya burung-burung yang beterbangan. Burung alap-alap, camar, hingga kormoran membuat langit Istanbul tampak semarak. Kota ini bagaikan magnet untuk burung-burung, tak lain karena lokasinya. Terletak di benua Asia dan Eropa dengan selat Bosphorus sebagai jembatan di antara keduanya, kota ini diberkahi arus udara yang nyaman untuk dilalui burung-burung yang bermigrasi. dewi pun tak melewatkan kesempatan untuk menatap dua sisi Istanbul dari atas kapal pesiar. Suhu udara yang masih berkisar pada belasan derajat celcius, dan angin yang bertiup cukup dingin tak mencegah kami untuk terus berdiri di atas dek. Pemandangan deretan istana dari zaman Ottoman, benteng-benteng batu, bangunan villa dari kayu, hingga taman dan teras restoran terasa lebih menarik daripada menghangatkan tubuh di dalam kabin kapal.
Setelah kapal pesiar kembali merapat ke daratan, kami kemudian memilih untuk menuju kawasan Galata. Ruas jalan dari batu-batu di atas kontur tanah menanjak dan menurun, kami lalui dengan berjalan kaki untuk sampai ke Galata. Hilir mudik mobil-mobil tak ketinggalan membuat suasana semakin hidup. Tapi semakin mendekat ke Galata Tower, arus mobil yang berseliweran mulai berkurang. Gedung-gedung dengan gaya arsitektur Neo Klasik mewarnai sebagian besar wajah Galata yang terletak di belahan Eropa. Sejarahnya berkaitan erat dengan orang-orang Genoa dan Venesia dari Italia, karena lokasinya yang berdekatan dengan Konstantinopel, ibukota kekaisaran Byzantine di masa lalu. Hingga kini, Galata masih menjadi pusat komunitas Eropa, dengan tempat-tempat hiburan seperti kafe, bar, hingga teater dan gedung opera. Sekolah-sekolah internasional dari Prancis, Inggris, Italia, juga Austria ada di kawasan ini. Situasi siang hari di lapangan dekat Galata Tower, cukup ramai dengan warga sekitar yang beristirahat makan siang, kaum muda yang berjalan-jalan berpasangan atau berkelompok, dan anak-anak yang baru pulang dari sekolah. Sebuah kedai kopi Italia terlihat ramai namun tetap tenang, ‘dijaga’ dua ekor anjing yang terkantuk-kantuk. Telinga anjing-anjing itu dipasangi tanda pengenal dari plastik, yang artinya mereka sudah disterilisasi dan divaksin anti rabies.
Sudah sampai di Galata, tak ada salahnya melanjutkan eksplorasi ke area sekitarnya. Jalan Serdar-? Ekrem dipenuhi butik fashion dan toko desain serta kafe yang mewakili kreativitas lokal. Udara sejuk dan obrolan seru dengan teman seperjalanan, membuat rasa lelah menyusuri jalan Serdar-? Ekrem tak terasa. Langkah kaki pun memasuki ?stiklal Caddesi dengan butik-butik label internasionalnya yang sudah tak asing. Tetapi bagi wisatawan dari Jakarta yang terbiasa dengan sejumlah mal di sudut kota, berbelanja bukanlah pilihan yang menarik di sini. Justru kucing-kucing yang berbulu tebal serta panjang lebih menarik perhatian. Mereka duduk diam di tepi jalan, tak bergeming saat lensa kamera membidik. Bisa jadi, perut kenyang berkat makanan pemberian warga sekitar membuat mereka tenang.
Dewi menunggu hingga pagi berikutnya untuk memulai penjelajahan di kawasan Sultanahmet. Bagian kota tua yang berada di wilayah Eropa ini adalah tempat berdirinya Museum Hagia Sophia dan Masjid Sultanahmet yang juga dikenal sebagai Blue Mosque. Sebuah lapangan membentang di antara dua bangunan yang mencerminkan kejayaan Turki di masa lalu itu. Orang-orang berjalan-jalan atau duduk-duduk di lapangan itu, sambil menikmati roti simit dengan olesan keju atau Nutella, atau makan es krim tanpa memedulikan udara dingin. Semua dibeli dari pedagang yang memarkir kendaraan niaganya di situ. Burung-burung dara yang beterbangan pun singgah di lapangan untuk mencari remah-remah roti, tanpa khawatir dikejar kucing-kucing yang juga bermain di sana. Duduk sejenak di lapangan itu, terasa seperti pilihan tepat untuk mencerna kemegahan arsitektur dan ornamen Blue Mosque serta Hagia Sophia. Kubah bertingkat-tingkat di Masjid Biru yang sama atraktifnya dilihat dari dalam maupun luar, dengan enam minaretnya, tak lain dari tempat beribadah atau berkontemplasi yang luar biasa. Sedangkan Hagia Sophia adalah tempat yang tak pernah membosankan untuk dikunjungi ulang, bagi mereka yang sudah pernah melihat isinya. Seperti selalu ada sudut baru yang menarik, yang sebelumnya tak terperhatikan. Seekor kucing yang setia ‘menjaga’ tempat itu selama bertahun-tahun, juga tak ketinggalan menjadi daya tarik Hagia Sophia. Gli, begitu kucing itu akrab disapa. Ia senang berpose anggun saat pengunjung museum berebutan memotretnya.
Istana Topkapi yang legendaris, juga bisa dicapai dengan berjalan kaki saja dari Sultanahmet Square. Sayang saat dewi berkunjung, istana ini sedang tutup. Sesaat kami berdiri saja mengagumi pintunya yang tinggi menjulang, dijaga oleh dua orang tentara bersenjata. Gagal singgah di Istana Topkapi, dewi beranjak menghampiri Basilica Cistern yang juga hanya dalam hitungan langkah dari lapangan. Tempat ini adalah penampungan air di bawah tanah yang terkesan megah dengan 336 pilar batu. Kami berjalan di lorong-lorong berlantai kayu di antara kolam, menikmati refleksi lampu-lampu kemerahan di permukaan air. Bangsa Romawi yang dulu memanfaatkan air dari penampungan ini untuk kebutuhan sehari-hari, sengaja melepas ikan-ikan untuk berenang di sana. Tujuannya, supaya menjadi indikator kalau ada musuh yang meracuni persediaan air mereka. Hingga kini, keturunan ikan-ikan itu masih berenang-renang di sana.
Bicara soal ikan, ini lah yang juga harus termasuk dalam menu bersantap di Istanbul. Pada suatu siang dewi menyempatkan diri ke Arnavutköy, kawasan suburban di tepi Selat Bosphorus. Daerah ini terkenal dengan restoran-restoran seafood yang baik, di samping villa-villa kayu gaya Ottoman yang tersebar di perbukitan, dan deretan yacht yang terparkir di pinggir laut. Rumah-rumah ibadah yaitu masjid, gereja, dan sinagog yang bertetangga dengan damai di kawasan ini, mencerminkan keberagaman latar belakang warga di sini. Sudah sejak lama pula di Arnavutköy berdiri Robert College, sekolah Amerika prestisius yang telah meluluskan para alumni terpandang, termasuk Orhan Pamuk sang novelis peraih Nobel.
Kedatangan dewi di kawasan ini disambut pemandangan pria-pria yang sedang memancing ikan, tepat di seberang restoran Sur Balik, tempat bersantap siang hari itu. Kami memilih meja di lantai teratas sehingga bisa makan sambil melihat hamparan laut biru dan kapal-kapal yang berlayar di permukaannya. Menu pescatarian atau serba ikan dan seafood tersaji di meja. Ada sup krim ikan dan kerang, calamari goreng, dan kebap ikan dengan sayuran. Roti dan buah serta minyak zaitun tak ketinggalan melengkapi menu. Penutupnya, buah-buahan dan baklava beserta teh atau kopi. Santap siang yang lengkap itu, penting untuk mengisi tenaga menuju jadwal acara berikutnya: berkunjung ke Spice Bazaar.
Bersebelahan dengan New Mosque di distrik Fatih, Spice Bazaar juga dikenal sebagai bazaar Mesir, antara lain karena dulu karavan pedagang rempah dari Mesir melewati Istanbul saat menuju ke Eropa. Luasnya tak sebanding dengan Grand Bazaar yang lebih populer, tetapi cocok bagi mereka yang sedang tak ingin lupa waktu. Para penjaga kios Turkish Delight, baklava, dan rempah-rempah sigap menyambut kami di pintu masuk. Tawaran untuk mencicipi kudapan yang dijual terlalu menarik untuk dilewatkan. Kami juga diperbolehkan mencoba apple tea dari gelas-gelas mungil khas setempat. Tak ada paksaan untuk membeli, tapi manisnya gula dan keramahan pria-pria Turki itu akhirnya menggerakkan kami berbelanja. Bagi dewi, kios yang menjual cangkir-cangkir mungil ala afternoon tea Inggris juga mengundang untuk dihampiri. Para penjaganya membiarkan saja kami meneliti koleksi mereka. Mereka tak sedikit pun merayu kami untuk membeli, namun justru membuat penasaran. Kios berikutnya yang membuat kami berlama-lama mengagumi dan memilih adalah Begonville, yang menjual handuk katun ala Turki dengan berbagai modifikasinya. Motif-motif garis, geometris atau tribal dalam warna monokrom atau pastel menggoda untuk dibawa pulang. Apalagi penjaga tokonya antusias memberi potongan harga. Gulungan-gulungan handuk berbagai ukuran pun pindah ke tas belanja.
Turki juga tak kalah membanggakan busana dari bahan kulit produksi mereka. Sejumlah outlet akan dengan senang hati mengatur peragaan busana untuk calon pembeli, bahkan di pagi hari. Sebut saja pukul sembilan. Salah satu label yang menarik perhatian dewi adalah Punto, dan kebetulan memiliki outlet yang bersebelahan dengan hotel tempat kami menginap. Punto mengekspor sejumlah besar produknya ke pusat-pusat mode dunia, dan berkolaborasi dengan rumah mode internasional seperti Gianfranco Ferre, Valentino, dan Nina Ricci. Etalase tokonya memamerkan koleksi jaket kulit dan mantel bulu, dan aksesori yang tampak hangat serta bergaya, apalagi ketika dilihat saat cuaca dingin. Saat disentuh, jaket kulit itu terasa halus, dan ringan ketika dipakai. Dewi mengira-ngira apakah musim hujan yang panjang di tanah air sudah berakhir ketika kami kembali. Tapi kalau pun sudah, rasanya tak salah menyimpan sehelai jaket kulit berdesain klasik untuk perjalanan berikut. Sampai berjumpa lagi, Istanbul! (MUT) Foto: MUT
Hari masih gelap saat bus kami yang dilengkapi wifi melintas. Kesibukan warga Istanbul rupanya sudah dimulai. Kami turun di sebuah hotel tak jauh dari bandara untuk sarapan. Hari belum juga terang. Menu makan pagi Turki yang lengkap tersedia di buffet. Kami memilih menikmatinya di teras berdinding kaca. Semangkuk sup mi mengingatkan akan sup alfabet dari masa kecil yang gurih namun ringan, cocok sebagai pembuka. Piring ke-dua berjodoh dengan börek, lapisan kulit pastry dan keju yang masih hangat, sucuk (sosis khas Turki), keju lokal, dan potongan paprika serta jamur dengan saus tomat. Kami menghabiskannya sementara langit Istanbul tampak berangsur-angsur terang di balik dinding kaca.
Pagi hari di kota pusat budaya Turki ditandai dengan munculnya burung-burung yang beterbangan. Burung alap-alap, camar, hingga kormoran membuat langit Istanbul tampak semarak. Kota ini bagaikan magnet untuk burung-burung, tak lain karena lokasinya. Terletak di benua Asia dan Eropa dengan selat Bosphorus sebagai jembatan di antara keduanya, kota ini diberkahi arus udara yang nyaman untuk dilalui burung-burung yang bermigrasi. dewi pun tak melewatkan kesempatan untuk menatap dua sisi Istanbul dari atas kapal pesiar. Suhu udara yang masih berkisar pada belasan derajat celcius, dan angin yang bertiup cukup dingin tak mencegah kami untuk terus berdiri di atas dek. Pemandangan deretan istana dari zaman Ottoman, benteng-benteng batu, bangunan villa dari kayu, hingga taman dan teras restoran terasa lebih menarik daripada menghangatkan tubuh di dalam kabin kapal.
Setelah kapal pesiar kembali merapat ke daratan, kami kemudian memilih untuk menuju kawasan Galata. Ruas jalan dari batu-batu di atas kontur tanah menanjak dan menurun, kami lalui dengan berjalan kaki untuk sampai ke Galata. Hilir mudik mobil-mobil tak ketinggalan membuat suasana semakin hidup. Tapi semakin mendekat ke Galata Tower, arus mobil yang berseliweran mulai berkurang. Gedung-gedung dengan gaya arsitektur Neo Klasik mewarnai sebagian besar wajah Galata yang terletak di belahan Eropa. Sejarahnya berkaitan erat dengan orang-orang Genoa dan Venesia dari Italia, karena lokasinya yang berdekatan dengan Konstantinopel, ibukota kekaisaran Byzantine di masa lalu. Hingga kini, Galata masih menjadi pusat komunitas Eropa, dengan tempat-tempat hiburan seperti kafe, bar, hingga teater dan gedung opera. Sekolah-sekolah internasional dari Prancis, Inggris, Italia, juga Austria ada di kawasan ini. Situasi siang hari di lapangan dekat Galata Tower, cukup ramai dengan warga sekitar yang beristirahat makan siang, kaum muda yang berjalan-jalan berpasangan atau berkelompok, dan anak-anak yang baru pulang dari sekolah. Sebuah kedai kopi Italia terlihat ramai namun tetap tenang, ‘dijaga’ dua ekor anjing yang terkantuk-kantuk. Telinga anjing-anjing itu dipasangi tanda pengenal dari plastik, yang artinya mereka sudah disterilisasi dan divaksin anti rabies.
Sudah sampai di Galata, tak ada salahnya melanjutkan eksplorasi ke area sekitarnya. Jalan Serdar-? Ekrem dipenuhi butik fashion dan toko desain serta kafe yang mewakili kreativitas lokal. Udara sejuk dan obrolan seru dengan teman seperjalanan, membuat rasa lelah menyusuri jalan Serdar-? Ekrem tak terasa. Langkah kaki pun memasuki ?stiklal Caddesi dengan butik-butik label internasionalnya yang sudah tak asing. Tetapi bagi wisatawan dari Jakarta yang terbiasa dengan sejumlah mal di sudut kota, berbelanja bukanlah pilihan yang menarik di sini. Justru kucing-kucing yang berbulu tebal serta panjang lebih menarik perhatian. Mereka duduk diam di tepi jalan, tak bergeming saat lensa kamera membidik. Bisa jadi, perut kenyang berkat makanan pemberian warga sekitar membuat mereka tenang.
Dewi menunggu hingga pagi berikutnya untuk memulai penjelajahan di kawasan Sultanahmet. Bagian kota tua yang berada di wilayah Eropa ini adalah tempat berdirinya Museum Hagia Sophia dan Masjid Sultanahmet yang juga dikenal sebagai Blue Mosque. Sebuah lapangan membentang di antara dua bangunan yang mencerminkan kejayaan Turki di masa lalu itu. Orang-orang berjalan-jalan atau duduk-duduk di lapangan itu, sambil menikmati roti simit dengan olesan keju atau Nutella, atau makan es krim tanpa memedulikan udara dingin. Semua dibeli dari pedagang yang memarkir kendaraan niaganya di situ. Burung-burung dara yang beterbangan pun singgah di lapangan untuk mencari remah-remah roti, tanpa khawatir dikejar kucing-kucing yang juga bermain di sana. Duduk sejenak di lapangan itu, terasa seperti pilihan tepat untuk mencerna kemegahan arsitektur dan ornamen Blue Mosque serta Hagia Sophia. Kubah bertingkat-tingkat di Masjid Biru yang sama atraktifnya dilihat dari dalam maupun luar, dengan enam minaretnya, tak lain dari tempat beribadah atau berkontemplasi yang luar biasa. Sedangkan Hagia Sophia adalah tempat yang tak pernah membosankan untuk dikunjungi ulang, bagi mereka yang sudah pernah melihat isinya. Seperti selalu ada sudut baru yang menarik, yang sebelumnya tak terperhatikan. Seekor kucing yang setia ‘menjaga’ tempat itu selama bertahun-tahun, juga tak ketinggalan menjadi daya tarik Hagia Sophia. Gli, begitu kucing itu akrab disapa. Ia senang berpose anggun saat pengunjung museum berebutan memotretnya.
Istana Topkapi yang legendaris, juga bisa dicapai dengan berjalan kaki saja dari Sultanahmet Square. Sayang saat dewi berkunjung, istana ini sedang tutup. Sesaat kami berdiri saja mengagumi pintunya yang tinggi menjulang, dijaga oleh dua orang tentara bersenjata. Gagal singgah di Istana Topkapi, dewi beranjak menghampiri Basilica Cistern yang juga hanya dalam hitungan langkah dari lapangan. Tempat ini adalah penampungan air di bawah tanah yang terkesan megah dengan 336 pilar batu. Kami berjalan di lorong-lorong berlantai kayu di antara kolam, menikmati refleksi lampu-lampu kemerahan di permukaan air. Bangsa Romawi yang dulu memanfaatkan air dari penampungan ini untuk kebutuhan sehari-hari, sengaja melepas ikan-ikan untuk berenang di sana. Tujuannya, supaya menjadi indikator kalau ada musuh yang meracuni persediaan air mereka. Hingga kini, keturunan ikan-ikan itu masih berenang-renang di sana.
Bicara soal ikan, ini lah yang juga harus termasuk dalam menu bersantap di Istanbul. Pada suatu siang dewi menyempatkan diri ke Arnavutköy, kawasan suburban di tepi Selat Bosphorus. Daerah ini terkenal dengan restoran-restoran seafood yang baik, di samping villa-villa kayu gaya Ottoman yang tersebar di perbukitan, dan deretan yacht yang terparkir di pinggir laut. Rumah-rumah ibadah yaitu masjid, gereja, dan sinagog yang bertetangga dengan damai di kawasan ini, mencerminkan keberagaman latar belakang warga di sini. Sudah sejak lama pula di Arnavutköy berdiri Robert College, sekolah Amerika prestisius yang telah meluluskan para alumni terpandang, termasuk Orhan Pamuk sang novelis peraih Nobel.
Kedatangan dewi di kawasan ini disambut pemandangan pria-pria yang sedang memancing ikan, tepat di seberang restoran Sur Balik, tempat bersantap siang hari itu. Kami memilih meja di lantai teratas sehingga bisa makan sambil melihat hamparan laut biru dan kapal-kapal yang berlayar di permukaannya. Menu pescatarian atau serba ikan dan seafood tersaji di meja. Ada sup krim ikan dan kerang, calamari goreng, dan kebap ikan dengan sayuran. Roti dan buah serta minyak zaitun tak ketinggalan melengkapi menu. Penutupnya, buah-buahan dan baklava beserta teh atau kopi. Santap siang yang lengkap itu, penting untuk mengisi tenaga menuju jadwal acara berikutnya: berkunjung ke Spice Bazaar.
Bersebelahan dengan New Mosque di distrik Fatih, Spice Bazaar juga dikenal sebagai bazaar Mesir, antara lain karena dulu karavan pedagang rempah dari Mesir melewati Istanbul saat menuju ke Eropa. Luasnya tak sebanding dengan Grand Bazaar yang lebih populer, tetapi cocok bagi mereka yang sedang tak ingin lupa waktu. Para penjaga kios Turkish Delight, baklava, dan rempah-rempah sigap menyambut kami di pintu masuk. Tawaran untuk mencicipi kudapan yang dijual terlalu menarik untuk dilewatkan. Kami juga diperbolehkan mencoba apple tea dari gelas-gelas mungil khas setempat. Tak ada paksaan untuk membeli, tapi manisnya gula dan keramahan pria-pria Turki itu akhirnya menggerakkan kami berbelanja. Bagi dewi, kios yang menjual cangkir-cangkir mungil ala afternoon tea Inggris juga mengundang untuk dihampiri. Para penjaganya membiarkan saja kami meneliti koleksi mereka. Mereka tak sedikit pun merayu kami untuk membeli, namun justru membuat penasaran. Kios berikutnya yang membuat kami berlama-lama mengagumi dan memilih adalah Begonville, yang menjual handuk katun ala Turki dengan berbagai modifikasinya. Motif-motif garis, geometris atau tribal dalam warna monokrom atau pastel menggoda untuk dibawa pulang. Apalagi penjaga tokonya antusias memberi potongan harga. Gulungan-gulungan handuk berbagai ukuran pun pindah ke tas belanja.
Turki juga tak kalah membanggakan busana dari bahan kulit produksi mereka. Sejumlah outlet akan dengan senang hati mengatur peragaan busana untuk calon pembeli, bahkan di pagi hari. Sebut saja pukul sembilan. Salah satu label yang menarik perhatian dewi adalah Punto, dan kebetulan memiliki outlet yang bersebelahan dengan hotel tempat kami menginap. Punto mengekspor sejumlah besar produknya ke pusat-pusat mode dunia, dan berkolaborasi dengan rumah mode internasional seperti Gianfranco Ferre, Valentino, dan Nina Ricci. Etalase tokonya memamerkan koleksi jaket kulit dan mantel bulu, dan aksesori yang tampak hangat serta bergaya, apalagi ketika dilihat saat cuaca dingin. Saat disentuh, jaket kulit itu terasa halus, dan ringan ketika dipakai. Dewi mengira-ngira apakah musim hujan yang panjang di tanah air sudah berakhir ketika kami kembali. Tapi kalau pun sudah, rasanya tak salah menyimpan sehelai jaket kulit berdesain klasik untuk perjalanan berikut. Sampai berjumpa lagi, Istanbul! (MUT) Foto: MUT
Author
DEWI INDONESIATRENDING RIGHT THIS VERY SECOND
FOOD & TRAVEL
CASA CUOMO, Simfoni Kuliner Italia di Jakarta