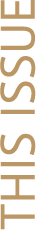Opini: Menilik Wajah Kita

Tilik bikin geger. Mungkin Wahyu Agung Prasetyo selaku sutradara maupun Siti Fauziah selaku pemeran utama tak pernah membayangkan film pendek yang mereka garap dua tahun silam malah menjadi terobosan terbesar bagi karier mereka. Tercatat, sejak mengudara pada 17 Agustus 2020 di YouTube, Tilik sudah ditonton lebih dari 20 juta kali.
Sepanjang sejarah film Indonesia, mungkin hanya Pengkhianatan G30S PKI yang bisa menyaingi skala kepenontonan sebesar itu. Itupun dengan catatan: tidak semua orang rela menontonnya. Tilik sebaliknya luwes singgah di kehidupan banyak orang melalui tautan yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Sosok Bu Tejo dirayakan sebagai ikon untuk zaman kabar burung ini, sementara Wahyu dan Siti ramai mendapat tawaran tampil di media, ajakan kolaborasi, bahkan proposal proyek. Kesuksesan Tilik tak pelak mengundang tanya. Bagaimana ceritanya sebuah film pendek lokal bisa menyita perhatian nasional?
Dugaan paling umum adalah kedekatan dengan penonton. Meski hampir sepenuhnya berbahasa Jawa, konten Tilik bisa dengan mudah dicerna oleh berbagai kalangan penonton. Paling menonjol tentunya sosok Bu Tejo, yang dianggap familiar dengan imajinasi populer masyarakat tentang sosok ibuibu. Masih ingat anekdot ‘motor matic sein kiri malah belok kanan’? Anekdot itu terlebih dulu populer di rimba internet dan seringkali disertai dengan gambar ibu-ibu berjilbab sebagai ilustrasi, bahkan sempat masuk sejumlah situs berita. Seiring berjalannya waktu, anekdot itu diwajarkan sebagai bagian dari imajinasi publik tentang sosok ibu-ibu. Melalui sosok Bu Tejo yang mulutnya tak bisa diatur itu, Tilik menggaungkan imajinasi yang sama.
Penokohan yang sejatinya problematis ini lantas dibungkus dengan tema yang berpotensi mengundang polemik lebih lanjut. Di satu sisi, budaya bergunjing yang menjadi inti kisah Tilik kadung lekat dengan stereotip ibu-ibu yang menjadi subjek film. Di sisi lain, topik yang sama terasa relevan dengan apa yang sedang kita lalui dewasa ini, ketika rimba media sosial diperlakukan sebagai ladang kebenaran tersendiri. Pembuat filmnya secara efektif mengolah tema itu dalam jalinan adegannya. Setiap momen berpijak pada pertanyaan tentang kebenaran lanturan Bu Tejo, yang kemudian diruncingkan pada sebuah kejutan yang mengecoh dugaan penonton.
Ndilalah, kecohan itu malah menyulut pergunjingan di luar film. Ada yang bilang Tilik membenarkan hoax dan itu sikap yang berbahaya di tengah iklim sosial saat ini. Ada yang menyebutnya sama sekali tidak mendidik. Ada juga yang bilang Tilik sebatas mau keren-kerenan bermain plot twist pada akhir film. Ada yang malah teringat kelakuan tetangga atau orang tua di kampung halaman. Tentunya, ada pula yang menempatkan Tilik sebatas tontonan hiburan yang seharusnya dilepaskan dari agenda politik ndakik-ndakik. Keriuhan ini saya rasa penting untuk kita sorot. Pasalnya, kapan terakhir kali publik kita ramai-ramai mempertanyakan pendirian sebuah film? Lebih spesifik lagi: kapan terakhir kali ada film Indonesia yang bisa mendorong beragam penonton untuk mempertanyakan batas sebuah tontonan?
Kita bisa mengingat kembali film-film yang sukses menghimpun lebih dari satu juta penonton beberapa tahun belakangan ini. Sebutlah Cek Toko Sebelah, My Stupid Boss, Ada Apa dengan Cinta? 2, Pengabdi Setan, Dilan 1990, Keluarga Cemara, Dua Garis Biru. Masing-masing dipahami, dinikmati, dan digemari atas semesta ceritanya. Terlepas dari suka dan tidak suka, penonton umumnya mengganggap Yogyakarta milik Rangga dan Cinta sebagai entitas yang berbeda dari Yogyakarta di dunia nyata, begitu juga Bandung milik Dilan dan Milea. Kisah mereka terkunci dalam semesta mereka sendiri, dengan sedikit ruang bagi penonton untuk menempatkan diri di dalamnya. Keramaian penonton pun umumnya terungkap sebagai hasrat—atau, untuk film seram, ketakutan—terhadap fantasi di layar.
Di ujung ekstrem satunya lagi, ada film yang ditanggapi publik tanpa mempedulikan isinya. Pada 2018, Kucumbu Tubuh Indahku dikenakan sejumlah petisi penolakan, lalu disusul penolakan penayangan oleh sejumlah pejabat daerah dan organisasi masyarakat, hanya karena film Garin Nugorho itu dituding mempromosikan LGBT dan melanggar nilai agama. Dalam kasus ini, semesta cerita dalam film sepenuhnya diabaikan. Tak ada pembahasan tentang budaya tari lengger yang melekat pada tokoh utama, tak ada pula sorotan terhadap pergulatan identitas yang dilakoni protagonis sepanjang lintasan kisahnya. Yang ada hanyalah pemaksaan agenda eksternal ke sebuah film.

Tilik mengisi ceruk yang unik. Sebagai film, ia dinikmati sebagai fantasi tapi juga membuka ruang untuk identifikasi. Representasi yang dihadirkan memang problematis, sehingga mengundang tudingan misoginis atau stereotip dari sejumlah pihak, tapi tidak sedikit juga yang merasa terhubung dengan sosok Bu Tejo. Nyatanya, bahkan di kalangan yang menganggap Tilik sebatas tontonan hiburan sekalipun, lumrah ditemukan pernyataan “Bu Tejo adalah kita”. Sosok-sosok lain pun juga tak luput dari perhatian penonton. Bisa dilihat dari silih bergantinya tokoh-tokoh kunci Tilik menjadi trending topic di media sosial—dari Bu Tejo, Yu Ning, Bu Tri, Dian, hingga Gotrek si supir truk.
Benang merah yang menghubungkan mereka semua: representasi masyarakat yang lain. Bu Tejo dan gerombolannya adalah wajah-wajah yang selama ini absen, atau seringnya ditampilkan sambil lalu, dalam sinema arus utama kita. Bisa dibilang mayoritas dari film panjang kita tengah mengalami gentrifikasi, seiring dengan makin eksklusifnya bioskop sebagai konsumsi borjuis urban. Alhasil, hanya kalangan sosial-ekonomi tertentu yang terbahasakan dalam film.
Kisah-kisah akar rumput sesekali memang bisa muncul, begitu juga panorama kehidupan rural maupun kegelisahan kalangan menengahbawah. Namun, kalaupun muncul, seringnya mereka dipandang dan diposisikan dari pucuk imajinasi borjuis urban tadi. Desa umumnya ditempatkan sebagai penegas atas kemajuan kota—atau, sebaliknya, sebagai lokasi calon pembangunan. Sementara itu kalangan menengahbawah dihadirkan sebagai pembanding moral—antara sebagai gerombolan yang kumuh dan tidak berakhlak, atau sebagai sosok yang tabah dan tetap harmonis dalam melakoni hidup serba kekurangan.
Tilik memungkinkan ‘masyarakat yang lain’ untuk tampil dalam kompleksitas mereka sendiri. Alih-alih dikotak-kotakkan dalam realitas sempalan, rombongan ibu-ibu di Tilik hadir dengan keragaman bahkan kontradiksi di antara mereka. Masing-masing tindakan mereka digerakkan oleh motivasi yang berbeda, sementara itu relasi mereka menyiratkan kerenggangan bahkan hierarki tersendiri. Bu Tejo, misalnya, dikisahkan menempati posisi ekonomi yang berbeda dari ibu-ibu lainnya, sehingga memiliki koneksi sosial yang lebih luas dan konsekuensinya punya lebih banyak bahan pergunjingan. Untuk kalangan yang umumnya dipukul rata sebagai ‘orang udik’ di film panjang, mereka menemukan ungkapan yang lebih dekat dengan pergulatan identitas mereka lewat film pendek.
Itulah kemewahan film pendek. Sebagai medium bercerita, ia bisa leluasa menjangkau realitas-realitas yang berada di pinggiran atau di sela-sela realitas yang lebih dominan disuarakan dalam lanskap media kita. Film pendek relatif bebas dari tuntutan pasar dan kekangan sensor, membuatnya lebih terbuka terhadap realitas-realitas yang dianggap ‘sensitif’ dan niche. Ongkos serta teknis produksinya pun ringkas, sehingga bisa diproduksi oleh beragam kalangan, dari lingkar pelajar sampai sineas profesional. Sepanjang keberadaannya di Indonesia, film pendek konsisten menjadi medium yang memperluas partisipasi publik dalam perfilman, baik sebagai pembuat maupun sebagai penonton film. Malahan film pendek adalah produk terbanyak dari ekosistem film di Indonesia. Setiap tahunnya, diperkirakan ada 800 sampai 1.000 film pendek yang diproduksi di Indonesia.

Saya pribadi selalu percaya: kalau ingin mengenal wajah Indonesia, tontonlah film pendeknya. Nyatanya, banyak dari realitas yang dianggap pinggiran atau sempalan itu sejatinya dilakoni oleh jutaan bahkan miliaran orang. Tilik menyentuh salah satu di antaranya, yang kemudian teramplifikasi melalui YouTube di tengah kebosanan akut selama pandemi. Fakta bahwa Tilik memilih timing dan sarana edar yang tepat perlu diapresiasi, tapi juga sulit mengelak bahwa ia berangkat dari realitas yang begitu menjejak, bahkan dibanding film-film panjang di bioskop sekalipun. Sebelum mengudara luas di internet, Tilik sudah tayang di sejumlah festival lokal dan layar tancap. Responsnya ramai untuk kalangan penonton festival. Nantinya, kalangan yang sama menjadi pemain kunci dalam menyebarluaskan film Tilik via media sosial, sebelum akhirnya meledak sebagai fenomena nasional.
Kesuksesan terbesar Tilik adalah memperkenalkan khalayak luas dengan sinema yang lain, yang kaya akan realitas-realitas yang selama ini belum terlalu terungkap. Pada saat yang sama, capaian Tilik sepatutnya menjadi momentum bagi pengadaan titik temu yang lebih beragam antara film dengan publik, juga bagi pengupayaan keragaman konten di publik. Setelah sekian lama menjadi bagian sunyi dari ekosistem perfilman nasional, film pendek kini mulai dilirik publik sebagai salah satu opsi tontonan. Sineas-sineas mulai merilis film pendeknya secara daring, ketika sebelumnya sering terbatas pada sirkuit festival semata.
Yang diuntungkan lebih dari perfilman Indonesia itu sendiri. Semakin beragam tontonan, semakin luas lingkar penonton yang dijangkau, semakin terbuka pula kita terhadap warna-warni wajah kita. (Adrian Jonathan Pasaribu*) Foto: Dok. Ravacana Films
*Penulis adalah salah satu pendiri Cinema Poetica, sebuah situs yang mengkaji film Indonesia yang dirintis pada Oktober 2010. Cinema Poetica berfokus pada produksi dan distribusi pengetahuan sinema bagi publik, sebagai tanggapan terhadap minimnya literatur tentang film di Indonesia, serta minimnya kajian tentang sinema Indonesia pada umumnya.