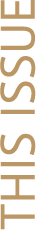Perjuangan Alissa Wahid untuk Rakyat Indonesia

Sebagai anak mantan presiden dan menyandang nama besar Wahid, Alissa Wahid sadar ia tak boleh terlena oleh ketenaran atau fasilitas sosial. Bagaimana pun, ia sudah memilih berjuang bersama rakyat, terutama mereka yang ada di akar rumput.
“Sejak kuliah, saya terbiasa berada di tengah warga desa, bahkan sampai Gunung Kidul. Waktu itu saya masuk ke Layanan Pendampingan Remaja di kampus, jadi saya ke sana untuk berceramah soal kehidupan remaja termasuk pencegahan narkoba. Hingga kini, saya selalu terjun langsung ke masyarakat. Dari kampung di Muntilan sampai Tentena dan Poso. Saya ingin memahami pengalaman dan aspirasi rakyat. Ini menjaga saya tetap terhubung dengan mereka dan tidak merasa jadi big shot.”
Sebesar apa pun tekadnya, Alissa pernah juga dilanda putus asa. Sekitar 2011-2012, ia menyaksikan banyak kasus kekerasan atas nama agama. Antara lain penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung menyusul persidangan kasus penistaan agama. Kasus lain terkait industri besar terjadi di Samarinda. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga, tak ditutup lagi seperti seharusnya. Sepuluh orang penduduk lokal terperosok ke dalamnya, termasuk bocah sembilan tahun. Sang ibu yang menuntut keadilan, malah diusir oleh perusahaan. Alissa melakukan advokasi, tapi pemerintah daerah hanya mengeluarkan teguran. Perusahaan melenggang tanpa hukuman sama sekali.
Semua ini membuat Alissa merasa mentok tembok. ‘Apakah keadilan sosial mustahil terwujud di negeri ini?’, pikirnya. Siapa sangka, ketika hatinya terpuruk, pertanyaan dari putra sulungnya membangkitkan kembali semangatnya. Ia mengatakan bahwa ia dan juga anak cucu dari anak-anak Alissa nanti bisa menikmati masa-masa sekarang karena ada yang berjuang untuk mereka dulu. Maka Alissa dan juga anak-anak mereka turut bersyukur karena para pejuang dulu lah yang berkorban untuk mereka sehingga mereka bisa merasakan ‘rumah’ yang terus disusun oleh anak dan cucu mereka nanti.
(EP) Foto: Shinta Meliza