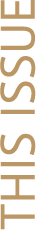Ay Tjoe Christine Berdiri Untuk Merdeka

Pagi masih remaja. Anak-anak sekolah baru saja ditinggal oleh para ibu yang perlu kembali beraktivitas. Ay Tjoe Christine salah satu dari para ibu itu yang baru saja tiba kembali ke rumah seusai mengantar buah hatinya ke sekolah. Lain waktu, ia dengan riang berkomunikasi telepon dengan seseorang ibu dari sahabat putranya di telepon. “Mau menitip jemput anaknya karena dia sedang ada urusan lain,” kata Christine sambil tersenyum. Wajahnya cerah. Menjadi ibu, baginya, bukan semata karena ia melahirkan Aran putranya, tapi juga karena ia “melahirkan” kembali dirinya. “Saya merasa jadi orang yang lebih baik dan punya tujuan hidup,” begitu selalu ia menggambarkan peristiwa besar itu.
Kehadiran Aran, buah hatinya membuatnya utuh dan tahu ke mana perjalanannya menuju. Menjadi seorang ibu tunggal bagi putranya, ia berusaha tegak dan kokoh. “Saya senang sekali ketika akhirnya merasa bisa tegak berdiri di kaki sendiri dan benar-benar berdaya ketika punya anak,” katanya. Sebuah persoalan saat itu, membuatnya harus pergi dari Yogyakarta, tempat di mana ia menetap kala itu. Ia memutuskan kembali ke Bandung. Tempat ia lahir dan tumbuh, untuk membuat sarang hangat bagi putra kecilnya. “Saat itu, saya seperti merasa ditodong sekaligus diragukan oleh diri sendiri. Rasanya diri saya bilang, ‘Kamu benar-benar akan bisa enggak jadi ibu untuk anak dan apakah kamu bisa berguna untuk seluruh keluarga?’” Christine mengatakan.
Kembali ke Bandung, setelah melewati badai besar, menjadi sebuah laku sabatikal bagi Christine. “Saya kembali lagi pada keluarga, pada rahim yang melahirkan saya. Saya memulai hidup lagi dari nol. Bukan dalam arti membangun karier, tapi membangun mental,” katanya. Christine berbenah dan mencoba membangun hidup bersama putranya. Berdua saja, dengan lingkaran kecil keluarga: ibu, ayah, kakak dan adiknya. “Saya kerap berpikir bahwa saya menjadi kuat karena memiliki beberapa teman. Namun di satu titik, saya merasa apa yang saya yakini tentang menjadi kuat itu ternyata ada salahnya dan cukup fatal. Maka begitu kembali ke Bandung untuk memulai hidup bersama Aran, saya mulai berbenah. Kembali ke Bandung, saya seperti baru bangun dari sebuah kelelapan,” katanya.
Di rumah baru mereka, Christine mengubah koordinat pusat kehidupan dari dirinya pada anaknya. “Awalnya berat. Cuma saya tahu transisi yang saya hadapi saat itu harus diatasi segera. Proses recovery dan penyadarannya tidak boleh berlangsung terlalu lama. Karena kalau tidak begitu, saya akan tidak berguna lagi,” katanya. Proses tersebut pula yang membuatnya tahu cara menjalani semua perannya dengan baik. “Saya bisa mempelajari bagaimana menjadi seniman, bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi anggota keluarga. Dengan pengalaman dan pengetahuan baru itu, saya merasa lebih merdeka dan berani berdiri sendiri. Tidak harus bergantung pada siapa-siapa selain pada Tuhan dengan segala kebesaran dan mukjizat-Nya,” Christine mengisahkan.
Berdaya baginya, adalah ketika ia melepaskan keinginannya untuk berdaya. Tumbuh di keluarga Tionghoa yang menerapkan budaya patriarkis, diam-diam ia menyimpan kemarahan atas diskriminasi perlakuan yang umumnya lebih mengutaman laki-laki ketimbang perempuan. Kemarahan yang menurutnya membuat ia kerap mencari solusi bagi persoalan-persoalan hidup saya secara keliru. “Banyak kesalahan dan benturan yang harus saya hadapi. Meski saat ini kalau mengenang lagi semuanya saya berpikir, barangkali memang saya melewati apa yang semestinya saya lewati, tapi kadang saya sendiri tidak paham apa yang membuat saya saat itu begitu ngotot dan akhirnya memilih semua pilihan saya. “Kenapa mesti begitu, ya?” adalah pertanyaan yang sering mengusik saya,” katanya. Kemarahan yang kemudian ia sadari membuat sisi kemanusiaannya tidak menjadi lebih baik. “Kita lantas jadi buas, karena berhasrat menjadi penakluk. Saya kemudian berpikir, bagaimana mengatasi itu dengan lebih baik,” Christine mengatakan.
Ia tak menutup mata pada fakta bahwa penindasan terhadap perempuan itu nyata ada. “Tapi saya pikir, alih-alih meratapi keadaan, lebih baik memikirkan bagaimana cara menumbuhkan kemanusiaan, kepercayaan diri, rasa berguna yang akan membuat mereka tumbuh dan muncul sebagai perempuan yang pantas,” kata Christine. Ia tak melihat perempuan yang berteriak memperjuangkan haknya sebagai langkah yang salah sebab semua orang memiliki cara masing-masing untuk memperjuangkan nasib. Namun ia melihat, membangun sesuatu dari dalam diri dan mencoba mengurai hal-hal yang menyebabkan rasa tertekan adalah cara yang lebih efektif. “Saya pikir, kita perlu memakai cara-cara yang kreatif untuk membongkar hegemoni patriarki dengan mengubah perspektif perempuan,” katanya.
Menurutnya, pola pikir yang melulu menempatkan perempuan sebagai korban harus diubah. “Misalnya, jangan lagi biarkan perempuan berpikir dirinya adalah korban ketika pasangannya melakukan kekerasan pada dirinya. Perempuan harus bisa berpikir bahwa ketika mengalami kekerasan, ia adalah manusia bebas yang bisa kreatif mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya,” kata Christine lagi. Ia menganalogikannya dengan seseorang yang tengah duduk di kursi pendek yang selalu harus menengadah untuk melihat orang lain yang bisa bangkit berdiri sejajar atau bahkan lebih tinggi dari orang yang tadinya harus ia lihat dengan kepala menengadah. Ia meyakini sebuah teori, bahwa dalam keadaan sama tinggi, seorang perempuan akan bisa memiliki perspektif yang berbeda yang membuatnya lebih merdeka.
(Indah S. Ariani)
Foto: Chris Bunjamin
Pengarah Gaya: Karin Wijaya
Busana: Tangan, F Budi, Domestikdomestik
Rias Wajah dan Tata Rambut: Marshya D. Martha