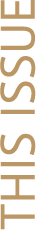Perkara Orisinalitas di Troso

“Apa yang pernah Anda dengan tentang Troso, itu semua benar,” kata Tommy Utama membuka presentasinya di panel diskusi World Ikat Textile Symposium 2019, 24 Agustus silam. Yang ia maksud adalah reputasi para penenun di Desa Troso, Jepara yang kerap mencatut motif-motif ikat dari daerah lain dan melabeli serta menjualnya sebagai ikat dari daerah yang dimaksud. Bukan dari Troso.
Imbasnya, banyak orang yang baru pertama mengoleksi ikat tertipu dan mencoreng nama Troso di kalangan pencinta kain ikat. Padahal, soal pencatutan motif ikat tradisional suatu daerah ini sejatinya bukan menjadi masalah bagi pembeli saja. Para penjual dan pengrajin ikat di Troso pun bisa kena tulah.
Masalahnya, kini komunitas-komunitas lokal di berbagai daerah tengah gencar mendaftarkan ragam kekayaan daerah mereka untuk mendapatkan geographical indication (GI). Konsultan Geoographical Indication Internasional Stephane Passeri menjelaskan GI adalah sejenis intelectual property atau “hak paten” yang digunakan untuk melindungi kekayaan budaya atau hayati dari suatu daerah.
Untuk mendaftarkan suatu bentuk kebudayaan dari suatu daerah, komunitas di daerah tersebut harus memberikan bukti-bukti yang menjadi kekhasannya. Hal ini bisa berupa teknik pembuatan dan penggunaan bahan lokal sebagai bahan bakunya.
Di Indonesia, perihal GI ini sudah dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam aturan itu dikatakan hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi geografis masih ada.
Artinya, apabila ada pelanggaran atas indikasi geografis tersebut meliputi pencatutan nama atau peniruan atas produk kebudayaan tersebut, maka produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis itu atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis bersangkutan bisa mengajukan tuntutan hukum.
Sudah banyak komunitas atau produsen yang mendaftarkan kekayaan daerahnya untuk mendapatkan indikasi geografis. Kini sudah ada 65 kekayaan daerah yang terdaftar sebagai indikasi geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meski seluruhnya masih merupakan kekayaan hayati dan olahan makanan, tetapi tak menutup kemungkinan indikasi geografis juga akan digunakan untuk melindungi produk-produk kebudayaan tradisional semacam ikat.

Saat itu terjadi, berarti masalah bagi para penenun Troso. Sementara, menenun adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat Troso. Di sana ikat dan tenun bukan semata soal cerita leluhur atau tradisi, melainkan soal sambungan hidup.
“Di Troso itu kerjaannya [masyarakat] menenun. Dari jam 8 sampai jam 3 sore itu mereka memang bekerja untuk menenun. Ada targetnya,” jelas Tommy yang selama dua tahun bekerja sama dengan Cita Tenun Indonesia untuk membina para penenun di Troso.
Memang, industri kain ikat dan tenun di Troso boleh dibilang masih jauh dari ideal. Ada banyak tengkulak dan oknum-oknum yang memasarkan barang dagangan mereka secara tidak jujur. Persaingan yang berat dan kondisi industri yang tak sehat membuat para penenun di sana akhirnya melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk bertahan.
Itu sebabnya para penenun di sana membuat motif-motif dari daerah lain yang sudah pasti digemari pasar untuk menafkahi hidup sehari-hari. Namun, para penenun di Troso seringkali dijadikan kambing hitam akan maraknya peredaran kain-kain ikat abal-abal. Sikap memusuhi tersebut, sambung Tommy, justru bukan pilihan bijak bagi kelangsungan ekosistem dan industri.
Itulah mengapa ia bersama Cita Tenun Indonesia selama 2013 hingga 2016 terjun langsung ke Desa Troso untuk meningkatkan kapasitas penenun di sana dan mendorong penggunaan pewarna alam serta teknik pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan industri masa kini.
Yang Tommy maksud dalam mengembangkan kapasitas penenun di Troso termasuk pula membina mereka untuk mengembangkan desain baru. “Jadi kami mengajak desainer tekstil, desainer produk, dan desainer grafis untuk menggali lagi budaya Troso dan budaya Jawa Tengah bagian utara secara umum agar mereka punya identitas sendiri,” jelas Tommy kepada Dewi.
Ia dan Cita Tenun Indonesia melakukannya dengan memberikan kelas intensif kepada beberapa kelompok penenun di Troso, termasuk dua kelompok penenun besar di sana untuk mengembangkan desain baru dan menggunakan pewarna alam. Kelas itu dilangsungkan sebanyak enam kali dengan masing-masing kelas berlangsung selama tiga hari. Hasil dari kelas tersebut kemudian diolah oleh para desainer yang tergabung dalam Cita Tenun Indonesia.
Motif-motif baru tersebut banyak terinspirasi dari budaya di Jepara yang dulunya merupakan kota pelabuhan. Selain itu motif-motif ukiran Jepara yang mahsyur pun jadi sumber inspirasi desain ikat baru dari Troso yang dikembangkan bersama Cita Tenun Indonesia.
Selain menyoal penciptaan desain-desain yang autentis dari para penenun Troso, hal yang juga menjadi perhatian utama Tommy dan Cita Tenun Indonesia di Troso ialah terciptanya jejaring antara para penenun di desa tersebut dan para desainer di kota-kota besar.
Menurutnya ini bisa jadi peluang inovasi dan kolaborasi bersama bagi para penenun dan desainer. Para desainer di Jakarta bisa membantu penenun-penenun di Troso dengan memberikan desain ikat yang hendak dibuat untuk pakaian mereka. Dengan begitu, para penenun di Troso tidak lagi terjebak mencatut motif-motif ikat dari Sumba, Bali, dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar. Ditambah lagi para penenun di Troso mempunyai kapasitas produksi yang cukup besar, bisa sampai sekitar 200 meter kain dalam sekali produksi, sehingga bisa membuat biaya produksi para desainer lebih efisien.
“Mereka skill-nya tinggi, tolong tuangkan kreativitas kalian tapi jangan dorong mereka untuk menyontek. Kuncinya di situ,” tutupnya tegas. (SIR). Foto: Dok. Tommy Utama.
Topic
FashionAuthor
DEWI INDONESIATRENDING RIGHT THIS VERY SECOND
FOOD & TRAVEL
CASA CUOMO, Simfoni Kuliner Italia di Jakarta