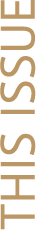Tanah Air Seorang Nomad Arahmaiani

Arahmaiani adalah satu dari sedikit seniman Indonesia yang dikenal di dunia internasional serta mendapat pujian. Iani, demikian ia biasa disapa, telah mengikuti belasan pameran bersama dan menyelenggarakan 10 pameran tunggal di berbagai negara.
Seni adalah panggilan jiwanya, sehingga ia memilih kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Ketika dosen memberi tugas melukis dengan cat minyak, ia justru melukis dengan arang. Alasannya, “Harga arang lebih murah dan memberi kesempatan bereksperimen.” Dosen marah. Ia tidak lulus mata kuliah tersebut. Iani lantas menggambar dan menulis puisi protes pada dinding koridor kampus. Lukisan-lukisan arangnya dipajang di sepanjang koridor. Pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia, ia mengkritik Orde Baru. Dibantu tiga teman, Iani menggambar tank baja dan menulis puisi di jalanan. Tentara menangkapnya. Proses interogasi berlangsung satu bulan. Iani memperoleh bebas bersyarat setelah dokter tentara menerangkan ia “menderita gangguan mental”. Demi keselamatan, seorang teman mengusulkan Iani pergi ke Australia. Orangtuanya setuju.
Di usia 22 tahun, Iani meninggalkan Indonesia. Ia bekerja di pasar Sydney, yang memberinya wawasan baru.Kehidupan komunal dengan aneka bangsa serta budaya membuka matanya tentang politik global. Ia gelisah, karena mengetahui bahwa Indonesia juga menjadi sasaran sekaligus terkena dampak. Pertanyaan tentang identitas menguat, sehingga ia memutuskan pulang ke Indonesia untuk menemukan lebih lanjut siapa dirinya.
Tiba di Jakarta, ia bertemu Bert Hermen, teman dari Belanda, yang mengajak berkunjung ke Bengkel Teater, yang dipimpin penyair dan dramaturg terkemuka WS Rendra. Tentu saja, ia masih berpenampilan ala punker, “Rambut pendek. Jaket paku-paku.” Rendra memberinya dua buku, Pararaton dan puisi epik Dante Alighieri, Divine Comedy. Buku Dante mengisahkan perjalanan jiwa menuju Tuhan. Pararaton atau “kitab raja-raja” adalah fiksi tentang riwayat raja-raja di Jawa yang melegitimasi kekuasaan feodal. Baginya, Rendra mengagumkan, “Mas Willy adalah orang Jawa yang berani mengkritik budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, mengkritik itu kualat.”
Pada 1987 Iani memperoleh beasiswa dari Belanda untuk belajar di sekolah seni rupa Jan Van Eyck. Tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia menolak memberinya surat keterangan karena ia masuk daftar hitam akibat aksi-aksi politiknya dulu. Ketika masalah teratasi, program beasiswa sudah berhenti. Ia tetap berangkat ke Belanda dan kuliah di Academie voor Beeldende Kunst pada 1991. Belum setahun kuliah, Iani harus pulang. Pemerintah Belanda mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, sehingga hubungan dua negara memburuk. “Orang Belanda di Indonesia disuruh pulang. Orang Indonesia di Belanda disuruh pulang,” kisahnya.
Ia kecewa, sakit selama setahun, kehilangan semangat hidup. Kakeknya dan teman-teman Bengkel Teater membantunya bermeditasi. Setelah pulih, ia semangat berkarya.
Pameran tunggal pertamanya berlangsung di Studio Oncor pada 1993, didukung penyair Toeti Herati. Tajuk pameran cukup kontroversial, Seks, Agama dan Coca Cola. Sebelum pameran dibuka ia menyadari dua karya ternyata menghilang, yakni Etalase dan Lingga-Yoni. Ray Sahetapy, pemilik Studio Oncor, memberitahu Iani bahwa sejumlah orang menuduhnya menghina Islam. Mereka menyatakan darahnya halal diminum.
Pameran tunggalnya di Frankfurt didukung Universitas Goethe dan Universitas Katolik dengan tujuan melengkapi perspektif yang ditampilkan pemerintah Indonesia secara resmi di Frankfurt Book Fair saat Indonesia menjadi tamu kehormatan, “Lalu ada diskusi dengan Werner Krauss, yakni bagaimana menanggapi persoalan-persoalan sosial politik Indonesia. Dia usul agar menampilkan karya saya dari zaman dulu sampai sekarang.”
Iani menyuarakan seni anti kekerasan, “Dalam prinsip tantangan, yang berlawanan direkonsiliasikan, karena dasarnya adalah welas asih.”
Perjalanannya untuk sampai di sini cukup panjang. Ia telah melalui masa-masa terberat yang mengantarnya menjadi warga dunia. Ketika ia benar-benar sendirian, maka berkarya adalah sebuah Tanah Air untuk pulang. (LC) Foto: Dok. Arahmaiani