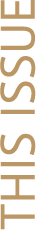Perjuangan Inayah Wahid untuk Indonesia yang Lebih Baik, Seperti yang Diimpikan Sang Ayah
Tahun 2000, negeri ini dipimpin oleh Abdurrahman Wahid, yang disumpah menjadi Presiden ke-4 Republik Indonesia. Inayah Wahid, sang anak bungsu pun merasakan perubahan dalam hidupnya. Sebagai anak presiden, ia harus mendapat pengawalan. Nay-demikian ia dipanggil, merasa risih. Ia tidak suka selalu diawasi dan diikuti, termasuk ketika kuliah. Diam-diam Nay kabur meninggalkan pengawal di kampus dan pulang ke rumah naik kereta. “Sampai di rumah, saya dimarahi Kak Allisa. Katanya meski Bapak dan Ibu tidak marah pada saya, tapi pengawal saya dihukum atasannya karena dianggap lalai dalam bertugas. Sejak hari itu saya sadar bahwa setiap pilihan hidup punya konsekuensi jangka panjang, tidak hanya apa yang kita pikir terbaik di saat itu saja,” ujar Inayah Wahid.
Inayah adalah anak ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan Sinta Nuriyah. Tiga kakaknya yaitu Alissa Wahid, Yenny Wahid, dan Anita Wahid. Anak-anak perempuan Gus Dur, tumbuh dengan ajaran bahwa mereka berhak melakukan apapun, asal bertanggung jawab. Nay mengaku, ia yang paling ‘provokatif’. Saat di bangku sekolah, ia pernah bolos satu bulan. Ayahnya dipanggil pihak sekolah. “Sampai di rumah bapak mengajak berdialog, ‘Kamu nantinya mau ngapain? Orang hanya bisa jadi pintar kalau belajar dan kerja keras.’ Dia nggak marah, tapi menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses.”
Saat ayahnya masih menjabat, Nay juga gemar berganti-ganti warna rambut. Gus Dur tidak melarang. “Beliau bilang, kamu sudah paham kalau secara fiqih mengecat rambut itu tidak boleh? Ini mungkin bikin kamu dihujat orang. Kalau siap bertanggung jawab, silahkan. Bapak ingin saya patuh karena paham, bukan nurut karena takut. Saya dididik untuk jadi perempuan mandiri yang bertanggung jawab,” kisah Nay. Ia mengakui ada beban berat sebagai anak Gus Dur. “Orang-orang sering berpikir kami adalah perpanjangan Gus Dur. Semua anak-anaknya harus sama seperti bapaknya. Masalahnya, mereka bikin standar yang mesti saya ikuti. Salah satu yang sering ditanyakan itu kenapa anak kyai kok nggak pakai hijab?” ujarnya. Ia menyadari identitasnya yang dikaitkan dengan dirinya sebagai perempuan, beragama Islam, turunan Jawa, dan orang Indonesia.
Semasa hidupnya, Gus Dur kerap membela orang-orang dan kelompok minoritas. “Dulu saya belum paham kenapa bapak begitu gigih memperjuangkan mereka. Sekarang saya mengerti. Rasanya menyakitkan jika kita melihat dari sisi yang tertindas,” ungkap Nay serius. Ia menilai masalah Indonesia saat ini bukan semata kurangnya pemahaman akan pluralisme, melainkan tidak adanya hukum yang kuat. “Mereka yang intoleran juga bagian dari perbedaan yang harus kita hargai. Masalahnya, ketika yang intoleran itu merasa berhak menyakiti orang lain yang dianggap tidak sama, lalu berbuat kekacauan, maka negara harus memastikan hukum bisa ditegakkan.” Ia menambahkan, “Sejak lama bangsa ini memang dididik untuk tidak merayakan perbedaan. Agama dibatasi hanya lima yang diakui negara, padahal ada ribuan keyakinan. Apakah negara ini sudah benar-benar menghargai perbedaan? Sejak dulu, yang minoritas tertindas, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak betul-betul terjadi.”
Menurutnya, hampir semua aspek perlu dibereskan. Pendidikan dan ekonomi harus dibenahi. Saya ingat bapak pernah berkata, mustahil perdamaian terwujud tanpa ada keadilan. Keadilan sosial, persamaan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia harus terwujud. Ini tugas semua orang, bukan hanya mereka yang duduk di bangku pemerintahan.” Setelah Gus Dur meninggal dunia, ada banyak orang dan kelompok minoritas yang tadinya ‘dilindungi’ Gus Dur kemudian khawatir. Siapa yang melindungi mereka setelah Gus Dur tidak ada? Pertanyaan besar untuk Nay dan tiga kakaknya. “Saya pikir alasan beliau cepat dipanggil Tuhan, jangan-jangan karena sudah waktunya perjuangan bapak tidak dibebankan hanya pada dirinya seorang. Saatnya kita semua harus meneruskan perjuangan beliau,” kata Inayah.
Keluarga Gus Gur memiliki ‘markas’ di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Namanya Griya Gus Dur. Setiap anak Gus Dur punya gerakannya masing-masing. Alissa mengepalai Lembaga Kemaslahatan Umat di Nahdlatul Ulama dan menggagas berdirinya Jaringan Gusdurian yang mengupayakan penyebaran pluralisme dan nilai toleransi. Yenny menangani Wahid Foundation. Anita menggaungkan anti korupsi. Dan Inayah dengan gerakan kaum muda. Keempatnya berusaha menjangkau problem dan situasi Indonesia dari berbagai titik. “Kami ingin meneruskan visi besar bapak soal Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera. Bukan berantem karena beda, tapi merayakan perbedaan,” tutur Inayah.
Upaya meneruskan perjuangan Gus Dur versi Inayah, diwujudkan melalui gerakan Positive Movement yang ia dirikan sejak 2006. Aksi kaum muda yang menyebarkan nilai-nilai kebahagiaan dan semangat positif dalam kehidupan. Baginya, untuk menuju perdamaian tidak melulu dengan dialog antar agama. Ia ingin menjangkau banyak orang, terutama pihak-pihak yang menilai pluralisme itu membahayakan. Melalui Positive Movement, Inayah bicara tentang kebahagiaan. “Semua orang jelas ingin bahagia.” Definisi bahagia menurutnya, bukan soal kesenangan karena mendapat sesuatu. “Bahagia adalah keseimbangan dan perdamaian. Bukan tentang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bahagia itu dicapai melalui perilaku ikhlas, bersyukur, jujur, menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain,” katanya. Tidak mengagetkan juga jika mulai 2016 kemarin, Inayah aktif di organisasi internasional, Green Peace Indonesia, “Kita bikin gerakan pemberdayaan kaum petani sekaligus advokasi jika diperlukan. Jika semua ini dilakukan, maka pluralisme terjadi secara otomatis tanpa kita harus berteriak.”
Di waktu senggangnya, ia menekuni dunia teater. Sejak SMA, bersama sahabatnya ia sering menonton teater. Ia juga pernah belajar akting di Teater Pagupon yang dipegang Ikatan Keluarga Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. “Teater itu menyenangkan. Saya suka semua aspek dari teater. Saya selalu kagum dan sering membayangkan diri saya berada di atas panggung teater,” kata Nay. Lulus SMA, ia ingin belajar teater dan kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Tetapi ibunya tidak menyetujui. Nay tidak gentar. Ia berkompromi dan akhirnya mengambil kuliah Sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Semua senang. Nay tetap bisa bermain teater di kampus dan sang ibu tidak marah. Bermain wayang orang arahan Jaya Suprana, ia kemudian sadar bahwa teater adalah bagian dalam hidupnya yang tidak mungkin ia lepaskan. Inayah pernah melakoni teater monolog Bukan Bunga Bukan Lelaki bersama Happy Salma dan Olga Lydia. Ia terlibat di drama musikal Kandil & Kampung Srundeng yang digagas Yayasan Sayap Ibu untuk penggalangan dana. Ia juga pernah berperan sebagai tukang ojek di salah satu serial televisi swasta.
Di antara empat anak Gus Dur, hanya Inayah yang berkecimpung di dunia seni. Yenny Wahid sempat kuliah Desain Komunikasi Visual, tapi memutuskan menjadi aktivis dan politisi serta mengurus Wahid Foundation. Punya tiga kakak perempuan memang tidak berarti harus memiliki banyak kesamaan. Inayah mengaku persaudaraannya jadi menyenangkan justru karena masing-masing berbeda. “Tetap ada kompromi dan saling menghormati,” tutur perempuan kelahiran 31 Desember 1983 itu.
Kembali pada pemikiran sang bapak, Inayah merasa bahwa sesungguhnya, apa yang diperjuangkan Gus Dur melampaui pemahaman pluralism, “Ketika Gus Dur mati-matian membela mereka yang berbeda agama dengannya, bahkan Ahmadiyah, atau orang Tionghoa, dan kaum marjinal lainnya, saya percaya yang beliau perjuangkan bukan “Cina-nya” atau “Ahmadiyah-nya”, melainkan kemanusiaannya. Fakta paling jelas menjadi manusia adalah kita semua itu beda. Saat kita bicara humanisme, maka kita bicara soal manusia yang jamak.” Bagi putri bungsu Gus Dur ini, ayahnya adalah sosok yang memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali.
Saat ini, Inayah sedang merintis untuk mendirikan sekolah menengah atas. Ia percaya, penyebaran nilai-nilai kehidupan yang baik, paling efektif dilakukan melalui pendidikan. “Saya sangat ingin mendirikan sekolah yang mengajarkan inklusivitas. Siapa pun tanpa kecuali bisa sekolah di sana. Tidak peduli apa agamanya dan keturunannya,” ucapnya sungguh-sungguh.
Inayah juga hendak melakukan napak tilas perjalanan Gus Dur. Dari Mesir tempat ayahnya kuliah, lalu sampai ke Eropa. Nay ingin menyelami apa yang pernah dilakukan dan dikunjungi ayahnya. “Saya yakin bahwa bapak menjadi orang yang egaliter, bijak, dan berpengetahuan luas salah satunya karena beliau rajin traveling. Setiap perjalanan itu membuka pikiran dan mengasah kepekaan kita sebagai manusia. Sehingga kita sanggup memahami apa itu kehidupan dan manusia secara utuh,” ujarnya, menutup pembicaraan. (RR) Foto: Denny Herliyanso, pengarah gaya: Yudith Kindangen, busana: Karen Millen, make up artist: Linda Kusumadewi
Inayah adalah anak ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan Sinta Nuriyah. Tiga kakaknya yaitu Alissa Wahid, Yenny Wahid, dan Anita Wahid. Anak-anak perempuan Gus Dur, tumbuh dengan ajaran bahwa mereka berhak melakukan apapun, asal bertanggung jawab. Nay mengaku, ia yang paling ‘provokatif’. Saat di bangku sekolah, ia pernah bolos satu bulan. Ayahnya dipanggil pihak sekolah. “Sampai di rumah bapak mengajak berdialog, ‘Kamu nantinya mau ngapain? Orang hanya bisa jadi pintar kalau belajar dan kerja keras.’ Dia nggak marah, tapi menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses.”
Saat ayahnya masih menjabat, Nay juga gemar berganti-ganti warna rambut. Gus Dur tidak melarang. “Beliau bilang, kamu sudah paham kalau secara fiqih mengecat rambut itu tidak boleh? Ini mungkin bikin kamu dihujat orang. Kalau siap bertanggung jawab, silahkan. Bapak ingin saya patuh karena paham, bukan nurut karena takut. Saya dididik untuk jadi perempuan mandiri yang bertanggung jawab,” kisah Nay. Ia mengakui ada beban berat sebagai anak Gus Dur. “Orang-orang sering berpikir kami adalah perpanjangan Gus Dur. Semua anak-anaknya harus sama seperti bapaknya. Masalahnya, mereka bikin standar yang mesti saya ikuti. Salah satu yang sering ditanyakan itu kenapa anak kyai kok nggak pakai hijab?” ujarnya. Ia menyadari identitasnya yang dikaitkan dengan dirinya sebagai perempuan, beragama Islam, turunan Jawa, dan orang Indonesia.
Semasa hidupnya, Gus Dur kerap membela orang-orang dan kelompok minoritas. “Dulu saya belum paham kenapa bapak begitu gigih memperjuangkan mereka. Sekarang saya mengerti. Rasanya menyakitkan jika kita melihat dari sisi yang tertindas,” ungkap Nay serius. Ia menilai masalah Indonesia saat ini bukan semata kurangnya pemahaman akan pluralisme, melainkan tidak adanya hukum yang kuat. “Mereka yang intoleran juga bagian dari perbedaan yang harus kita hargai. Masalahnya, ketika yang intoleran itu merasa berhak menyakiti orang lain yang dianggap tidak sama, lalu berbuat kekacauan, maka negara harus memastikan hukum bisa ditegakkan.” Ia menambahkan, “Sejak lama bangsa ini memang dididik untuk tidak merayakan perbedaan. Agama dibatasi hanya lima yang diakui negara, padahal ada ribuan keyakinan. Apakah negara ini sudah benar-benar menghargai perbedaan? Sejak dulu, yang minoritas tertindas, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak betul-betul terjadi.”
Menurutnya, hampir semua aspek perlu dibereskan. Pendidikan dan ekonomi harus dibenahi. Saya ingat bapak pernah berkata, mustahil perdamaian terwujud tanpa ada keadilan. Keadilan sosial, persamaan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia harus terwujud. Ini tugas semua orang, bukan hanya mereka yang duduk di bangku pemerintahan.” Setelah Gus Dur meninggal dunia, ada banyak orang dan kelompok minoritas yang tadinya ‘dilindungi’ Gus Dur kemudian khawatir. Siapa yang melindungi mereka setelah Gus Dur tidak ada? Pertanyaan besar untuk Nay dan tiga kakaknya. “Saya pikir alasan beliau cepat dipanggil Tuhan, jangan-jangan karena sudah waktunya perjuangan bapak tidak dibebankan hanya pada dirinya seorang. Saatnya kita semua harus meneruskan perjuangan beliau,” kata Inayah.
Keluarga Gus Gur memiliki ‘markas’ di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Namanya Griya Gus Dur. Setiap anak Gus Dur punya gerakannya masing-masing. Alissa mengepalai Lembaga Kemaslahatan Umat di Nahdlatul Ulama dan menggagas berdirinya Jaringan Gusdurian yang mengupayakan penyebaran pluralisme dan nilai toleransi. Yenny menangani Wahid Foundation. Anita menggaungkan anti korupsi. Dan Inayah dengan gerakan kaum muda. Keempatnya berusaha menjangkau problem dan situasi Indonesia dari berbagai titik. “Kami ingin meneruskan visi besar bapak soal Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera. Bukan berantem karena beda, tapi merayakan perbedaan,” tutur Inayah.
Upaya meneruskan perjuangan Gus Dur versi Inayah, diwujudkan melalui gerakan Positive Movement yang ia dirikan sejak 2006. Aksi kaum muda yang menyebarkan nilai-nilai kebahagiaan dan semangat positif dalam kehidupan. Baginya, untuk menuju perdamaian tidak melulu dengan dialog antar agama. Ia ingin menjangkau banyak orang, terutama pihak-pihak yang menilai pluralisme itu membahayakan. Melalui Positive Movement, Inayah bicara tentang kebahagiaan. “Semua orang jelas ingin bahagia.” Definisi bahagia menurutnya, bukan soal kesenangan karena mendapat sesuatu. “Bahagia adalah keseimbangan dan perdamaian. Bukan tentang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bahagia itu dicapai melalui perilaku ikhlas, bersyukur, jujur, menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain,” katanya. Tidak mengagetkan juga jika mulai 2016 kemarin, Inayah aktif di organisasi internasional, Green Peace Indonesia, “Kita bikin gerakan pemberdayaan kaum petani sekaligus advokasi jika diperlukan. Jika semua ini dilakukan, maka pluralisme terjadi secara otomatis tanpa kita harus berteriak.”
Di waktu senggangnya, ia menekuni dunia teater. Sejak SMA, bersama sahabatnya ia sering menonton teater. Ia juga pernah belajar akting di Teater Pagupon yang dipegang Ikatan Keluarga Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. “Teater itu menyenangkan. Saya suka semua aspek dari teater. Saya selalu kagum dan sering membayangkan diri saya berada di atas panggung teater,” kata Nay. Lulus SMA, ia ingin belajar teater dan kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Tetapi ibunya tidak menyetujui. Nay tidak gentar. Ia berkompromi dan akhirnya mengambil kuliah Sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Semua senang. Nay tetap bisa bermain teater di kampus dan sang ibu tidak marah. Bermain wayang orang arahan Jaya Suprana, ia kemudian sadar bahwa teater adalah bagian dalam hidupnya yang tidak mungkin ia lepaskan. Inayah pernah melakoni teater monolog Bukan Bunga Bukan Lelaki bersama Happy Salma dan Olga Lydia. Ia terlibat di drama musikal Kandil & Kampung Srundeng yang digagas Yayasan Sayap Ibu untuk penggalangan dana. Ia juga pernah berperan sebagai tukang ojek di salah satu serial televisi swasta.
Di antara empat anak Gus Dur, hanya Inayah yang berkecimpung di dunia seni. Yenny Wahid sempat kuliah Desain Komunikasi Visual, tapi memutuskan menjadi aktivis dan politisi serta mengurus Wahid Foundation. Punya tiga kakak perempuan memang tidak berarti harus memiliki banyak kesamaan. Inayah mengaku persaudaraannya jadi menyenangkan justru karena masing-masing berbeda. “Tetap ada kompromi dan saling menghormati,” tutur perempuan kelahiran 31 Desember 1983 itu.
Kembali pada pemikiran sang bapak, Inayah merasa bahwa sesungguhnya, apa yang diperjuangkan Gus Dur melampaui pemahaman pluralism, “Ketika Gus Dur mati-matian membela mereka yang berbeda agama dengannya, bahkan Ahmadiyah, atau orang Tionghoa, dan kaum marjinal lainnya, saya percaya yang beliau perjuangkan bukan “Cina-nya” atau “Ahmadiyah-nya”, melainkan kemanusiaannya. Fakta paling jelas menjadi manusia adalah kita semua itu beda. Saat kita bicara humanisme, maka kita bicara soal manusia yang jamak.” Bagi putri bungsu Gus Dur ini, ayahnya adalah sosok yang memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali.
Saat ini, Inayah sedang merintis untuk mendirikan sekolah menengah atas. Ia percaya, penyebaran nilai-nilai kehidupan yang baik, paling efektif dilakukan melalui pendidikan. “Saya sangat ingin mendirikan sekolah yang mengajarkan inklusivitas. Siapa pun tanpa kecuali bisa sekolah di sana. Tidak peduli apa agamanya dan keturunannya,” ucapnya sungguh-sungguh.
Inayah juga hendak melakukan napak tilas perjalanan Gus Dur. Dari Mesir tempat ayahnya kuliah, lalu sampai ke Eropa. Nay ingin menyelami apa yang pernah dilakukan dan dikunjungi ayahnya. “Saya yakin bahwa bapak menjadi orang yang egaliter, bijak, dan berpengetahuan luas salah satunya karena beliau rajin traveling. Setiap perjalanan itu membuka pikiran dan mengasah kepekaan kita sebagai manusia. Sehingga kita sanggup memahami apa itu kehidupan dan manusia secara utuh,” ujarnya, menutup pembicaraan. (RR) Foto: Denny Herliyanso, pengarah gaya: Yudith Kindangen, busana: Karen Millen, make up artist: Linda Kusumadewi