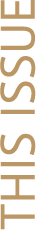Opini: Jurang Pemisah Perempuan dan Kekuasaan

Baru-baru ini Indonesia merayakan Hari Ibu. Seperti biasa, semua orang mengunggah foto-foto terbaik bersama ibunda tercinta diiringi kata-kata manis di bawah foto. Meski di kehidupan nyata, banyak di antara kita yang hidup berjarak dari ibu masing-masing, tak ada yang salah ketika kita mengapresiasi mereka yang melahirkan kita ke dunia di Hari Ibu. Sayangnya, apresiasi kepada para ibu ini kerap kali gagal mengingatkan kembali makna Hari Ibu di Indonesia.
Tak seperti di negara-negara lain, Hari Ibu di Indonesia sejatinya merupakan sebuah peringatan atas gerakan politik para perempuan di masa silam. Inilah peringatan Kongres Perempuan I yang diselenggarakan pada 22-25 Desember 1928 dan melahirkan enam tuntutan, yakni penambahan sekolah bagi perempuan; mendorong peraturan tunjangan bagi janda dan anak-anak pegawai negeri sipil; memberikan beasiswa bagi perempuan; mendirikan suatu lembaga untuk mengentaskan buta huruf, kursus kesehatan, serta memberantas perkawinan anak; dan mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).
Jika menengok sejarah itu, tentu kita patut berbangga bagaimana Indonesia dulu memiliki budaya pergerakan perempuan yang progresif, masif, terstruktur, dan efektif. Budaya yang kian lama kian tergerus sebagaimana makna Hari Ibu yang tadinya memperingati Hari Kebangkitan Perempuan dan peran perempuan sebagai “Ibu Bangsa” pun turut tereduksi.
Tentu ada banyak faktor yang mendorong reduksi Makna tersebut. Salah satunya adalah afirmasi atas peran-peran domestik perempuan sepanjang Orde Baru. Bagaimana di masa itu, perempuan-perempuan diperbolehkan berkegiatan hanya dalam kapasitasnya sebagai istri dari pegawai atau pejabat, baik itu di tataran sipil atau militer. Seperti dilansir Historia, selama Orde Baru hanya ada segelintir organisasi perempuan dan semuanya berada dalam kendali pemerintah. Tiga yang utama adalah PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, sementara organisasi perempuan lainnya tergabung dalam Kowani dengan ideologi Pancadharma Wanita yang intinya menempatkan perempuan hanya sebagai pendamping suami. Di masa ini pula, citra “perempuan yang baik” dibentuk bahwa ia adalah perempuan yang patuh, pendiam, dan perawat keluarga.
Gap Ambisi
Kini, gerakan perempuan di Indonesia pelan-pelan mulai dibangun kembali. Meskipun sama sekali bukan perkara mudah. Komentar-komentar sumbang tak pernah absen mengiringi jalan pergerakan perempuan. “Perempuan itu seperti sengaja dijauhkan dari kekuasaan,” kata politisi muda Partai Solidaritas Indonesia, Dara Nasution kepada Dewi di kantor DPP PSi beberapa waktu lalu. Pernyataan itu muncul di sela pembicaraan kami tentang halangan-halangan apa saja yang dihadapi perempuan kini untuk maju sebagai politisi atau menjabat posisi-posisi strategis di bidang apapun.
Mulai dari halangan sistemis dari partai politik, misalnya dalam konteks keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, hingga hambatan yang datang dari diri sendiri dalam bentuk ketidakpercayaan diri. Dampaknya kemudian adalah kesenjangan ambisi antara perempuan dan laki-laki dalam mengejar kuasa.

Dalam buku It Still Takes a Candidate (2010), Jennifer L. Lawless dan Richard L. Fox menjelaskan adanya ketimpangan rasa percaya diri antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki cenderung merasa percaya diri bahkan tentang kemampuan-kemampuan yang belum mereka kuasai dan cenderung lebih percaya diri tentang hal-hal yang mereka kuasai. Sementara perempuan, cenderung meragukan kompetensi dan kualifikasinya, meksipun secara objektif hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan bisa dikatakan berimbang.
Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja dalam ruang hampa. Perbedaan perlakuan serta didikan antara perempuan dan laki-laki sedari kecil punya andil besar. Dara menjelaskan, ada standar-standar yang diamini masyarakat luas tentang sosok atau karakter “perempuan yang baik” adalah perempuan yang sebisa mungkin menyeimbangkan kehidupan rumah tangganya dan karier publiknya. “Perempuan itu seperti harus membayar harga yang lebih mahal, bekerja lebih keras. Kita dibesarkan dengan pandangan bahwa kita harus memenuhi standar yang berbeda,” ujar politisi muda berusia 24 tahun itu.
Pada akhirnya, internalisasi akan kompetensi diri dan apa-apa yang membuat seorang perempuan terlihat baik menjadi salah satu halangan terbesar bagi perempuan untuk mengejar posisi-posisi strategis. Utamanya di politik. “Jadi perempuan sendiri merasa politik bukan untuk mereka. Padahal representasi gender yang substansial itu sangat penting,” tutup Dara. (SIR). Foto: Tody Harianto.