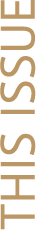Bias Kelas
Wacana soal “sustainability”, utamanya di industri mode, sama sekali bukan barang baru. Sudah sejak lama aktivis-aktivis di industri ini menyuarakan perkara kesinambungan operasionalnya. Ya, pada awalnya urusan “sustainability” di bidang fashion lebih berat membicarakan seputar kesejahteraan pekerja ketimbang persoalan lingkungan. Meskipun ketika itu, persoalan lingkungan juga sudah turut dibahas.
Ada beberapa asumsi mengapa kemudian isu tentang keberlangsungan industri menjadi seksi ketika ia dikaitkan dengan isu krisis lingkungan kini dan tidak ketika ia dikaitkan dengan isu kesejahteraan pekerja dulu. Pertama, ialah bahwa karena kini masalah lingkungan sudah sebegitu parahnya sehingga sulit untuk kita mengalihkan perhatian. Kedua, persoalan kesejahteraan pekerja, terutama buruh berupah rendah adalah hal yang dirasa jauh oleh kebanyakan kelas menengah.
Andhyta menjelaskan, bahkan ketika ia dikaitkan dengan wacana akan krisis lingkungan pun masih banyak kelas menengah yang menutup mata akan masalah lingkungan. Hasil survey YouGov-Globalism Project menunjukkan 18% orang Indonesia dari total 1.001 responden menyatakan tidak percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh perbuatan manusia. Dalam survey itu memang tidak dijelaskan secara rinci dari kelas mana responden berasal. Akan tetapi dari diskusi di ruang publik, kita bisa melihat betapa masyarakat kelas bawah masih kerap disalahkan setiap kali terjadi bencana seperti banjir. Alasan mereka kurang teredukasi menjadi salah satu argumentasi.
Akan tetapi ada satu perspektif yang selalu luput, yaitu bahwa justru kelas menengah ataslah yang justru menyumbang emisi karbon terbesar. Inilah kelas yang setiap kali selalu membawa kendaraan pribadi ketimbang kendaraan publik. Kelas yang apartemen tempat mereka tinggal menyedot air tanah Jakarta hingga membuat banjir daerah di sekitar, tetapi dirinya sendiri terlindungi. Kelas yang setidaknya setahun sekali merencanakan liburan ke luar negeri. Hal-hal yang semuanya mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan.
Hal ini dijelaskan pula dalam laporan Vox dari hasil riset Stephanie Moser dan Silke Kleinhückelkotten berjudul “Good Intents, Low Impact”. Dalam riset tersebut Moser dan Kleinhückelkotten menemukan fakta bahwa para self-claim pencinta lingkungan yang berasal dari tingkat ekonomi-sosial tinggi cenderung menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak, terhitung dari lahan yang mereka gunakan untuk tempat tinggal, energi yang digunakan, jumlah konsumsi daging, tingkat penggunaan mobil pribadi, hingga liburan. Sementara justru masyarakat kelas menengah bawahlah yang akan lebih merasakan dampaknya.
Ambil contoh kasus banjir di Jakarta awal tahun silam. Saat itu beredar foto aerial yang menampakkan sebuah komplek apartemen tetap aman dari banjir dengan kolam renangnya yang masih berwarna biru, sementara di luar tembok mereka banjir menggenang dengan air kecoklatan. Atau kasus pandemi yang kita alami sekarang ini. Pandemi COVID-19 pada dasarnya menyebar dengan cepat akibat perjalanan lintas-negara yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas menengah dan menengah atas, tetapi dampaknya justru dirasakan paling parah oleh mereka yang berada di kelas menengah bawah. Tanpa menyadari ketimpangan ini, pada akhirnya kampanye sustainable lifestyle yang dilakukan, seperti namanya, hanya akan menjadi sebuah gaya hidup. Bukan mewujudkan sistem baru.
“Makanya, menurut saya perubahan itu mesti terjadi lebih sistematis,” ujar Andhyta. Artinya perubahan yang menyangkut ke mana para investor menaruh uang mereka dan bagaimana pemerintah membuat regulasi. “Karena konsumen itu cenderung autopilot. They just buy stuff.”
Peran pemerintah dalam mengintervensi pasar untuk mewujudkan sistem yang lebih langgeng memang krusial. Terutama dalam menjembatani ketimpangan di masyarakat. Meski belum ada penelitian lebih lanjut tentang ini, tetapi fakta menunjukkan ada korelasi antara peran pemerintah mewujudkan sistem yang berkesinambungan (sistem kesehatan mumpuni, redistribusi sumber-sumber daya, layanan publik dan jaring pengaman sosial, pembatasan polusi udara, dan kemampuan untuk mengoreksi kegagalan pasar) dan tingkat ketimpangan masyarakatnya. Ambil contoh negara-negara Skandinavia. Andhyta pun mengamini hal tersebut. “I don’t know if it’s a causation, but there is definitely correlation. Karena kalau pemerintahnya mulai memberlakukan pajak dengan lebih agresif, ada intervensi yang benar, dan retribusi untuk bikin sistem jaring pengaman sosial yang lebih baik, itu adalah indikator dari pemerintah yang fungsional. Dan berlaku kebalikannya,” jelasnya.
Pun ketegasan dari pemerintah seperti itu juga akan menjadi jaminan bagi para pelaku swasta untuk serius mengubah model bisnis mereka. Ambil contoh Uni Eropa yang sudah berkomitmen untuk beralih 100% ke energi terbarukan sebelum 2050. “Hal itu kemudian menjadi sinyalemen ke pasar untuk beralih ke energi terbarukan. Biarpun sekarang belum biayanya belum efisien, tapi paling tidak para pelakunya sudah mendapat jaminan jangka panjang atas investasi mereka,” jelas Andhyta.
Di Indonesia, pemerintah bukannya tidak punya perhatian ke isu ini. Lingkungan hidup sudah masuk ke dalam salah satu dari tujuh sektor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di situ tertera beberapa rencana pemerintah untuk menurunkan jumlah pembakaran hutan, menurunkan sampah, serta mengurangi polusi udara dan laut. Pemerintah juga sudah memasang target bauran energi 2025 hingga 30% untuk batu bara, 25% untuk minyak bumi, 23% untuk energi baru dan terbarukan (EBT), serta 22% untuk gas. Namun, memang pemerintah kita masih bergulat dengan komitmen eksekusinya yang inkonsisten. Tercermin dari banyaknya pembangkit listrik batu bara yang baru dibangun di zaman Joko Widodo. Pula subsidi baru bara dan adanya peraturan prosentase harga untuk sumber daya dari panel matahari.