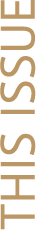Jika melihat tema-tema acara atau bahasa-bahasa pemasaran produk selama satu-dua tahun terakhir, ada satu istilah yang secara konstan akan Anda temui: “sustainable” atau “sustainability”. Atau “keberlangsungan” dalam bahasa Indonesia. Wacana tentang keberlangsungan itu kian memikat perhatian publik setelah pidato berapi-api Greta Thunberg: “Our house is on fire!” serunya, dan dunia ikut terbakar semangatnya.
Setelah itu seruan soal gaya hidup dan bisnis yang sustainable terus bergema, berulang, hingga tersaturasi maknanya sedemikian rupa hingga akhirnya identik dengan persoalan lingkungan. Padahal sebetulnya urusan sustainability adalah masalah hajat hidup. Ini lebih kepada masalah kita semua ketimbang masalah bumi. Dan karenanya jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan mengenakan pakaian linen, menyetok tote bag, atau sedotan besi.
Mari kita preteli urusan sustainability ini. Let’s kil the jargon! Kita mulai dari yang paling mendasar. Apa itu sustainability alias keberlangsungan? Salah satu definisi yang diusung oleh organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan World Bank ialah tentang memastikan “pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kebutuhan di masa yang akan datang”. Untuk itu, di dalamnya terdapat tiga elemen penting yang saling berkait, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Peneliti kebijakan publik dan ekonom lingkungan, Andhyta F. Utami menjelaskan model bisnis dikatakan sustainable menurut definisi-definisi organisasi internasional apabila ia bisa menghasilkan nilai ekonomi, dan di saat yang bersamaan juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Atau dalam bahasanya sendiri, “Bagaimana manusia beraktivitas dengan cara yang memungkinkan manusia untuk terus bertahan hidup.”
Jadi jelas, urusan sustainability ini bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi tentang menyelamatkan hidup dan peradaban kita hingga jauh ke masa yang akan datang. Kedengaran lebih egois memang, tapi begitulah adanya. Dan memang sudah kodratnya manusia sebagai makhluk yang egoistis. Egoisme adalah bagian yang inheren dari kehidupan di alam semesta, bahkan hingga ke level gen, Richard Dawkins telah menjelaskan argumennya secara rinci dan mendetail di buku The Selfish Gene. Ia menuliskan insting egois kita sebagai mesin kelestarian menyebabkan, “Acapkali tindakan yang tampak altruistik sesungguhnya adalah tindakan egois yang terselubung.” So, no shame.
Selanjutnya adalah apakah konsep bisnis yang berkesinambungan bisa diwujudkan dalam sistem ekonomi-politik kapitalistik seperti yang berjalan sekarang? Terutama dalam konteks mode. Industri mode, sebagaimana industri gaya hidup dan hiburan lainnya, seperti film, buku, musik, seni, dan sebagainya tumbuh dan berkembang dari ekses. Dalam hal ini ekses kapital. Bahkan dalam hal inovasi teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan sekalipun, ekses adalah sebuah keniscayaan.
Andhyta lebih lanjut menjelaskan, sejatinya bukan ide dasar kapitalisme tentang free market yang mendorong kompetisi dan memproduksi seefisien mungkin yang bermasalah. Melainkan market failure atau kegagalan pasar. Salah satu bentuk kegagalan pasar misalnya dari bagaimana sistem kapitalistik memberikan lebih banyak insentif-insentif jangka pendek. Hal ini terlihat nyata dari bagaimana keputusan-keputusan bisnis suatu perusahaan diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan dalam kerangka jangka waktu kuartal. Dampaknya, ada pengabaian akan implikasi jangka panjang yang krusial dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. “Karena itu bukan kepentingan jangka pendek mereka,” katanya kepada Dewi.
Selain itu, masalah kedua dari sistem kapitalistik yang berlangsung saat ini adalah eksternalitas, atau “biaya” yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga produksi suatu barang. Andhyta mengambil contoh pembebasan lahan untuk hutan kelapa sawit dengan cara pembakaran.
“Membakar itu adalah opsi paling murah untuk membuka lahan. Tapi sebenarnya yang tidak dimasukkan ke biaya produksi yang dia keluarkan di akhir itu adalah semua dampak kesehatan, lingkungan, dan juga perubahan iklim,” kata Andhyta. Misalnya dampak kebakaran lahan gambut yang menurut estimasi World Bank, membuat Indonesia mengalami kerugian hingga US$ 16,1 miliar atau setara Rp 221 triliun pada 2015 dan US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 73 triliun pada 2019.
Kedua hal ini juga tercermin dari upah buruh murah. Termasuk di industri mode. Sudah rahasia umum bahwa praktik produksi barang mode kerap melibatkan sweatshop di negara-negara berkembang yang mempekerjakan orang dengan upah tak layak dan dalam kondisi kerja buruk. Upah buruh di industri mode yang terlampau murah ini merupakan bentuk kegagalan pasar, di mana banyak brand besar sekadar mementingkan efisiensi biaya dengan memilih negara atau pemasok termurah tanpa mengecek atau mengevaluasi praktik operasional mereka. Ini adalah bentuk eksternalitas karena dampak upah yang terlampau rendah tidak diperhitungkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Dampak-dampak itu antara lain, kualitas hidup pekerja yang rendah dan menyulitkan perkembangan mereka. Sehingga memperlebar kesenjangan.