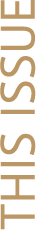Kisah Saras Dewi, Dosen Filsafat Universitas Indonesia
Saras Dewi tumbuh dan besar di pulau Bali. Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengenang kembali ke masa silam. “Bali menempati porsi besar yang membentuk siapa saya sekarang,” cerita Yayas.
Kecintaannya pada alam mungkin telah terbentuk sejak dini, tapi sifat kritisnya terhadap pelestarian alam mulai terbangun ketika ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu SMU tempat ia bersekolah hendak diperluas. Pohon-pohon perlu dipotong supaya sekolah punya lahan lebih. Salah satunya pohon ketapang berukuran sangat besar dan sudah sangat tua usianya. Yayas mencintai pohon tersebut. Tak ingin pohon tersebut ikut ditebang, ia pun memberanikan diri untuk berargumen pada pihak sekolah. “Menurut pihak sekolah, pohon harus dipotong demi kemajuan pendidikan. Pertanyaan saya, kenapa harus pohonnya yang dikorbankan? Mengapa kita harus membangun sesuatu dengan mengorbankan lingkungan hidup?” cerita Yayas. Kejadian itu mengendap lama di pikirannya tanpa pernah mendapat jawaban yang memuaskannya. Sang pohon pun tetap ditebang, dan Yayas lulus SMU. Ia pergi ke Jakarta dan memilih untuk berkuliah ilmu filsafat.
Lulus kuliah hasrat belajarnya belum terpuaskan, maka ia pun melanjutkan ke jenjang S2 hingga S3 Filsafat di Universitas Indonesia. Saat mengambil gelar doktor, ia kembali menekuni persoalan lingkungan hidup. “Penguji disertasi menanyakan, saya punya argumentasi apa untuk membela pohon? Pohon tidak bisa bicara, apa lagi bilang sakit. Bagaimana jika memang kodratnya harus begitu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang kemudian berusaha saya pecahkan sepanjang karier,” kata Yayas yang menuntaskan studi S3-nya di usia 29 tahun.
Kini, selain menempati posisi Kepala Program Studi Filsafat di Universitas Indonesia ia mengisi hari dengan aktif mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia menjadi dosen untuk mata kuliah filsafat timur, filsafat lingkungan hidup, etika lingkungan hidup, filsafat teknologi, filsafat sastra, dan eksistensialisme.
Ditanya apa tantangan dari profesinya saat ini, ia menjawab cepat, “Filsafat adalah dunianya laki-laki.” Karena paham ia berada di area yang didominasi pria, Yayas harus berusaha dua kali lebih keras dari yang seharusnya. Awal mengajar, ia amat sering dipandang rendah oleh koleganya. Perempuan, muda, dan dosen. Fakta yang membuat sebagian orang mudah meremehkan. Tapi Yayas tidak mundur. “Cobaan itu justru jadi sebab yang bikin kita mau kerja lebih keras. Jika ada orang menyepelekan, kita justru harus buktikan sebaliknya.”
Menurut Yayas, setiap persoalan perlu pemikiran dan pengetahuan yang lebih baik dan lebih akurat. Kampus menjadi tempat yang sangat berperan untuk itu. “Tugas (ilmu) filsafat adalah mampu membawa teori-teori di dalam kelas menjadi nyata di kehidupan luar kelas. Filsafat harus muncul menjadi ilmu yang mengajarkan pengetahuan sekaligus kepekaan.”
Meski ia lebih banyak berativitas di dunia pendidikan, nama Saras Dewi kini banyak dikenal berkaitan dengan aksi tegasnya menolak proyek reklamasi Teluk Benoa, wilayah konservasi alam di Bali yang oleh pemerintah ingin dikembangkan menjadi wilayah pariwisata. “Saya tidak menentang program pariwisata pemerintah, tetapi pernahkan terpikir bahwa orang datang ke Indonesia bukan untuk melihat negara ini seperti Dubai? Mereka ingin melihat tradisi dan budaya Indonesia. Jadi jangan alam lingkungannya yang dihancurkan,” demikian ia menyuarakan pendapatnya.
Pemikiran-pemikiran Yayas menjelma dalam kesehariannya. Setiap hari, Yayas sebisa mungkin tidak memakai plastik. Saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Yayas terlihat memakai botol minum yang bisa dipakai berulang. Ia juga selalu membawa tas kain supaya tidak menggunakan kantong plastik. “Apa yang kita pakai menjadi pernyataan secara etis tentang siapa kita. Saya tidak akan mengonsumsi produk-produk yang bermasalah etikanya.”
Menjadi seorang vegan sejak usia 14 tahun, Yayas tidak mengonsumsi dan tidak mengenakan produk yang memakai kulit hewan. Dimulai dengan tidak makan daging sapi, lalu ayam, kemudian seafood. Beberapa tahun terakhir Yayas juga tidak mengonsumsi susu, telur, dan keju. “Tidak ada alasan kenapa saya jadi vegan, selain karena saya sangat menyayangi hewan. Tidak pernah terpikir dan tidak tega saya makan mereka,” kata Yayas.
Tak lama lagi, Yayas selesai menjabat Kepala Program Studi Filsafat UI. Lalu apa yang akan ia lakukan kemudian? Dibantu Universitas Indonesia, Yayas kini tengah merampungkan pembangunan museum Sang Hyang Dedari di Bali. Museum ini nantinya akan bisa dimanfaatkan warga sekitar sebagai infrastruktur wisata desa ramah lingkungan, sekaligus menjadi acuan untuk program penelitian budaya. Ini akan menjadi prioritasnya setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala program studi Filsafat UI. “Saya senang melakukan kegiatan budaya dan seni. Yang tidak melulu untuk tujuan uang. Rasa-rasanya amat dangkal kalau dalam hidup ini, kita melakukan sesuatu hanya demi uang,” kata Yayas menutup percakapan. (RR) Foto: dok. dewi
Kecintaannya pada alam mungkin telah terbentuk sejak dini, tapi sifat kritisnya terhadap pelestarian alam mulai terbangun ketika ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu SMU tempat ia bersekolah hendak diperluas. Pohon-pohon perlu dipotong supaya sekolah punya lahan lebih. Salah satunya pohon ketapang berukuran sangat besar dan sudah sangat tua usianya. Yayas mencintai pohon tersebut. Tak ingin pohon tersebut ikut ditebang, ia pun memberanikan diri untuk berargumen pada pihak sekolah. “Menurut pihak sekolah, pohon harus dipotong demi kemajuan pendidikan. Pertanyaan saya, kenapa harus pohonnya yang dikorbankan? Mengapa kita harus membangun sesuatu dengan mengorbankan lingkungan hidup?” cerita Yayas. Kejadian itu mengendap lama di pikirannya tanpa pernah mendapat jawaban yang memuaskannya. Sang pohon pun tetap ditebang, dan Yayas lulus SMU. Ia pergi ke Jakarta dan memilih untuk berkuliah ilmu filsafat.
Lulus kuliah hasrat belajarnya belum terpuaskan, maka ia pun melanjutkan ke jenjang S2 hingga S3 Filsafat di Universitas Indonesia. Saat mengambil gelar doktor, ia kembali menekuni persoalan lingkungan hidup. “Penguji disertasi menanyakan, saya punya argumentasi apa untuk membela pohon? Pohon tidak bisa bicara, apa lagi bilang sakit. Bagaimana jika memang kodratnya harus begitu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang kemudian berusaha saya pecahkan sepanjang karier,” kata Yayas yang menuntaskan studi S3-nya di usia 29 tahun.
Kini, selain menempati posisi Kepala Program Studi Filsafat di Universitas Indonesia ia mengisi hari dengan aktif mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia menjadi dosen untuk mata kuliah filsafat timur, filsafat lingkungan hidup, etika lingkungan hidup, filsafat teknologi, filsafat sastra, dan eksistensialisme.
Ditanya apa tantangan dari profesinya saat ini, ia menjawab cepat, “Filsafat adalah dunianya laki-laki.” Karena paham ia berada di area yang didominasi pria, Yayas harus berusaha dua kali lebih keras dari yang seharusnya. Awal mengajar, ia amat sering dipandang rendah oleh koleganya. Perempuan, muda, dan dosen. Fakta yang membuat sebagian orang mudah meremehkan. Tapi Yayas tidak mundur. “Cobaan itu justru jadi sebab yang bikin kita mau kerja lebih keras. Jika ada orang menyepelekan, kita justru harus buktikan sebaliknya.”
Menurut Yayas, setiap persoalan perlu pemikiran dan pengetahuan yang lebih baik dan lebih akurat. Kampus menjadi tempat yang sangat berperan untuk itu. “Tugas (ilmu) filsafat adalah mampu membawa teori-teori di dalam kelas menjadi nyata di kehidupan luar kelas. Filsafat harus muncul menjadi ilmu yang mengajarkan pengetahuan sekaligus kepekaan.”
Meski ia lebih banyak berativitas di dunia pendidikan, nama Saras Dewi kini banyak dikenal berkaitan dengan aksi tegasnya menolak proyek reklamasi Teluk Benoa, wilayah konservasi alam di Bali yang oleh pemerintah ingin dikembangkan menjadi wilayah pariwisata. “Saya tidak menentang program pariwisata pemerintah, tetapi pernahkan terpikir bahwa orang datang ke Indonesia bukan untuk melihat negara ini seperti Dubai? Mereka ingin melihat tradisi dan budaya Indonesia. Jadi jangan alam lingkungannya yang dihancurkan,” demikian ia menyuarakan pendapatnya.
Pemikiran-pemikiran Yayas menjelma dalam kesehariannya. Setiap hari, Yayas sebisa mungkin tidak memakai plastik. Saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Yayas terlihat memakai botol minum yang bisa dipakai berulang. Ia juga selalu membawa tas kain supaya tidak menggunakan kantong plastik. “Apa yang kita pakai menjadi pernyataan secara etis tentang siapa kita. Saya tidak akan mengonsumsi produk-produk yang bermasalah etikanya.”
Menjadi seorang vegan sejak usia 14 tahun, Yayas tidak mengonsumsi dan tidak mengenakan produk yang memakai kulit hewan. Dimulai dengan tidak makan daging sapi, lalu ayam, kemudian seafood. Beberapa tahun terakhir Yayas juga tidak mengonsumsi susu, telur, dan keju. “Tidak ada alasan kenapa saya jadi vegan, selain karena saya sangat menyayangi hewan. Tidak pernah terpikir dan tidak tega saya makan mereka,” kata Yayas.
Tak lama lagi, Yayas selesai menjabat Kepala Program Studi Filsafat UI. Lalu apa yang akan ia lakukan kemudian? Dibantu Universitas Indonesia, Yayas kini tengah merampungkan pembangunan museum Sang Hyang Dedari di Bali. Museum ini nantinya akan bisa dimanfaatkan warga sekitar sebagai infrastruktur wisata desa ramah lingkungan, sekaligus menjadi acuan untuk program penelitian budaya. Ini akan menjadi prioritasnya setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala program studi Filsafat UI. “Saya senang melakukan kegiatan budaya dan seni. Yang tidak melulu untuk tujuan uang. Rasa-rasanya amat dangkal kalau dalam hidup ini, kita melakukan sesuatu hanya demi uang,” kata Yayas menutup percakapan. (RR) Foto: dok. dewi
Author
DEWI INDONESIATRENDING RIGHT THIS VERY SECOND
FOOD & TRAVEL
CASA CUOMO, Simfoni Kuliner Italia di Jakarta