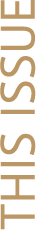Jejak Penebusan Sinematik Lisabona Rahman

Dua hari dalam seminggu, ia mengerjakan proyek restorasi untuk 13 film yang tersimpan di Pusat Perfilman Usmar Ismail (PPUI). Gedungnya berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Semua film tadi diproduksi sebelum kemerdekaan. Di ruang kerjanya di lantai lima, perempuan mungil ini tekun membersihkan pita-pita seluloid yang sudah tua dan sabar menambal bagian-bagian yang rusak.
“Sahabat saya adalah selotip, pisau bedah, alkohol dan cotton bud,” tutur Lisabona Rahman, penulis kritik film yang kini menekuni dunia restorasi film. Kami bertemu di restoran mi, di sebelah kantornya pada akhir bulan lalu.
Rentang waktu pembuatan 13 film itu antara tahun 1935 sampai tahun 1942. Secara jumlah, film pra kemerdekaan sangat sedikit. Ia memerinci sebabnya, “Sejak pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan sampai tahun 1948, nyaris tidak ada produksi film cerita. Pada tahun 1945, produksi bahkan film berhenti total. Bioskop tutup, karena perang. Ada jam malam.”
Ruang bawah tanah PPUI menjadi tempat penyimpanan film-film tadi, yang ditumpuk dan digulung dalam rak-rak penyimpanan. Temperaturnya terjaga, sedangkan kelembapannya tidak. Lisa sedih, “Akibatnya banyak film rusak.” Usmar Ismail yang namanya disematkan pada lembaga itu adalah Bapak Perfilman Nasional. “Setelah 1949, kata ‘nasional’ menjadi sangat penting, karena ‘nation’ Indonesia baru lahir. Dampaknya, film-film sebelum 1949 seperti dianggap tidak penting,” ucapnya. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949.
Berbeda dengan film pasca kemerdekaan yang dinilai memiliki muatan sosial dan kebangsaan, film pra kemerdekaan dianggap sekadar hiburan yang berisi dongeng dan fantasi. Tapi ia tidak percaya. “Ketika mempelajari sastra populer, misalnya, kita justru mengetahui bahwa cerita yang dianggap picisan itu memberi gambaran tentang situasi sosial zaman tertentu. Melalui film-film yang tersisihkan ini, saya ingin tahu seperti apa masyarakat yang mengkonsumsi dan menciptakannya,” ujar Lisa, seraya mengunyah mi. Film-film pra kemerdekaan terinspirasi oleh cerita-cerita 1001 Malam, berupa cerita fantasi, seperti Aladin dan Lampoe Wasiat, ataupun berisi cerita kepahlawanan, seperti Srigala Item dan Matjan Berbisik. Realisme dalam film Indonesia dimulai ketika ada yang membaca naskah-naskah Barat, yang diawali generasi Usmar Ismail dan angkatan sebelumnya Andjar Asmara, seorang wartawan dan penulis skenario.
Lisa bertekad menekuni restorasi film setelah menonton karya Usmar Ismail, Tiga Dara (1956), yang mengetengahkan drama keluarga dan percintaan. Ia menontonnya untuk pertama kali pada 2007. Sejak itu, tiap bulan Maret, ia yang menjadi koordinator bioskop di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, menyelenggarakan festival bertajuk Sejarah adalah Sekarang dan memutar film tersebut. Meski kesal film favoritnya sudah dalam keadaan memprihatinkan, ia tidak menyerah, “Setelah saya telusuri, rupanya ada ilmu tersendiri untuk merestorasi film.”
Pada 2011, Lisa berangkat ke Belanda dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar di jurusan Preservation and Presentation of the Moving Image, University of Amsterdam.
“Antara tahun 2011 dan 2012, saat saya mulai kuliah di sana, Yayasan Pusat Film Indonesia mengirim Tiga Dara ke Belanda untuk direstorasi. Yayasan ini berdiri sebelum saya meninggalkan Indonesia. Saya turut mendirikannya. Orlow Seunke, salah seorang pendiri yang aktif, mengupayakan restorasi itu,” kenangnya.
Namun, perubahan drastis terjadi di Belanda. Politikus beraliran kanan Geert Wilders memimpin parlemen. Ia memangkas anggaran institusi kebudayaan secara besar-besar, sehingga Nederlands Film Museum, sekarang bernama Eye Institute, yang menerima Tiga Dara tak dapat meneruskan proyek restorasi. Krisis ekonomi mulai melanda Belanda, yang sudah menggerogoti Eropa dan Amerika Serikat sejak 2008. Anggaran kebudayaan dianggap Wilders tidak penting, lalu menjadikannya sasaran empuk pengetatan biaya negara.
Tak berapa lama setelah kabar sedih itu, ia menengok proses restorasi film Lewat Djam Malam (1954), karya lain Usmar Ismail, yang tengah berlangsung di L’immagine Ritrovata, laboratorium film di Bologna, Italia. Lewat Djam Malam mengisahkan kekecewaan bekas tentara pejuang pasca proklamasi saat mengetahui praktik korupsi kawan seperjuangannya dulu. Proyek restorasi film itu didanai oleh National Museum of Singapore, yang merupakan proyek sampingan dari proyek utama untuk mempublikasikan katalog film Indonesia yang disusun JB Kristanto. “Dulu dia wartawan Kompas dan sekarang sudah pensiun. Sahabatnya, seorang kritikus film Singapura, tertarik menerjemahkan katalog tersebut ke dalam Bahasa Inggris. Dia ingin saat katalog itu diluncurkan, sebuah film yang menjadi favorit JB Kristanto turut ditayangkan,” tutur Lisa. Proyek ini dulu tak luput dari keterlibatannya. Pada 2010, ia sempat membantu mencari film tersebut dan menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat restorasi.
Akhirnya Lisa memutuskan magang di Bologna, “Dan sempat terpikir untuk membawa Tiga Dara ke sana.”
Dalam proses restorasinya, Lewat Djam Malam turut didukung yayasan film yang didirikan Martin Scorsese, sutradara terkemuka dunia asal Italia. Pada 2012, Lewat Djam Malam menjadi film pembuka Festival Film Cannes untuk kategori klasik. Persepsi publik terkena imbas. “Orang mulai melihat proyek itu bergengsi, lalu orang-orang kaya mau memberikan uangnya,” tuturnya.
Selama magang, ia merestorasi film-film dari berbagai negara, “Dari yang umurnya 15 tahun sampai 100 tahun.” Setelah lulus kuliah pada 2013, ia ditawari bekerja di L’immagine Ritrovata .
Lisa tidak menampik bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan tukang, “Tapi tukang yang dibekali pengetahuan ilmiah dan filosofi yang baik.” Ia menjelaskan profesi yang memiliki sejarah panjang ini, “Teknisi arsip atau archiver sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sampai sekarang dan mereka tak luput dari tekanan kepentingan politik yang berbeda-beda. Sebab arsip adalah pusat pemikiran.”
Tiga Dara, film yang mengubah jalan hidupnya, kemudian mengalami perubahan nasib. Pada 2015, film itu akhirnya dibawa ke laboratorium di Bologna. Perusahaan swasta di Indonesia, SA Film, mendanai proyek restorasinya. Lisa senang, “Ternyata saya bisa ikut membantu prosesnya dengan ilmu yang sudah saya miliki.”
Merestorasi adalah upaya untuk memulihkan apa yang hilang atau rusak. Ia bersikap kritis terhadap definisi serta praktik “restorasi” yang membabi-buta, “Tujuannya bukan mencipta sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Tapi ada perusahaan-perusahaan komersial yang cenderung mengartikan restorasi sebagai cara membuat film yang direstorasi itu seperti film yang baru disyuting kemarin. Artinya, tidak ada yang asli lagi. Selain itu, ahistoris.”
Ia anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya seorang diplomat. Ibunya putus kuliah, lalu mendampingi sang suami bertugas dari satu negeri ke negeri lain. Keduanya orang Minang. Mereka dijodohkan. Ia menyebut ayahnya ‘bujang lapuk’, “Mungkin dia terlalu sibuk dengan karier. Usia Ayah lebih tua 20 tahun dari Ibu.” Lisa lahir 41 tahun lalu di Lisabon, Portugal. Pengalaman hidupnya berpindah-pindah bersama keluarga hingga usia 17 tahun membuat ia merasa nilai-nilai hidupnya berasal dari semua tempat yang mereka pernah tinggal. Katanya, “Saya terbiasa hidup di mana manusia itu harus struggle dan independen.”
Film pertama yang ia tonton adalah serial Star Wars: Return of the Jedi. Ia menonton bersama sepupu-sepupunya di sebuah bioskop di Kairo, Mesir, “Mungkin itu tahun 1982 atau 1983.” Tapi itu bukan film yang paling mengesankan Lisa. Film-film yang mengesankannya tak lain dari film-film Indonesia, yang dipinjam sang ayah dari koleksi kedutaan untuk diputar di rumah, seperti Gita Cinta dari SMA dan Nakalnya Anak-Anak.
“Ketika teman-teman saya yang lebih dulu kembali ke Indonesia menonton film Catatan Si Boy, saya panik sekali. Mengapa saya ketinggalan menyaksikan kejadian sepenting itu,” katanya, seraya terbahak.
Ia tiba-tiba tercenung, mengingat semua yang sudah lampau, mencoba menarik garis dari masa silam ke masa kini, “Barangkali upaya saya melestarikan film adalah penebusan terhadap masa-masa yang terlewatkan untuk film, masa-masa yang hilang.” (LC) Foto: Dhany Indrianto.
“Sahabat saya adalah selotip, pisau bedah, alkohol dan cotton bud,” tutur Lisabona Rahman, penulis kritik film yang kini menekuni dunia restorasi film. Kami bertemu di restoran mi, di sebelah kantornya pada akhir bulan lalu.
Rentang waktu pembuatan 13 film itu antara tahun 1935 sampai tahun 1942. Secara jumlah, film pra kemerdekaan sangat sedikit. Ia memerinci sebabnya, “Sejak pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan sampai tahun 1948, nyaris tidak ada produksi film cerita. Pada tahun 1945, produksi bahkan film berhenti total. Bioskop tutup, karena perang. Ada jam malam.”
Ruang bawah tanah PPUI menjadi tempat penyimpanan film-film tadi, yang ditumpuk dan digulung dalam rak-rak penyimpanan. Temperaturnya terjaga, sedangkan kelembapannya tidak. Lisa sedih, “Akibatnya banyak film rusak.” Usmar Ismail yang namanya disematkan pada lembaga itu adalah Bapak Perfilman Nasional. “Setelah 1949, kata ‘nasional’ menjadi sangat penting, karena ‘nation’ Indonesia baru lahir. Dampaknya, film-film sebelum 1949 seperti dianggap tidak penting,” ucapnya. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949.
Berbeda dengan film pasca kemerdekaan yang dinilai memiliki muatan sosial dan kebangsaan, film pra kemerdekaan dianggap sekadar hiburan yang berisi dongeng dan fantasi. Tapi ia tidak percaya. “Ketika mempelajari sastra populer, misalnya, kita justru mengetahui bahwa cerita yang dianggap picisan itu memberi gambaran tentang situasi sosial zaman tertentu. Melalui film-film yang tersisihkan ini, saya ingin tahu seperti apa masyarakat yang mengkonsumsi dan menciptakannya,” ujar Lisa, seraya mengunyah mi. Film-film pra kemerdekaan terinspirasi oleh cerita-cerita 1001 Malam, berupa cerita fantasi, seperti Aladin dan Lampoe Wasiat, ataupun berisi cerita kepahlawanan, seperti Srigala Item dan Matjan Berbisik. Realisme dalam film Indonesia dimulai ketika ada yang membaca naskah-naskah Barat, yang diawali generasi Usmar Ismail dan angkatan sebelumnya Andjar Asmara, seorang wartawan dan penulis skenario.
Lisa bertekad menekuni restorasi film setelah menonton karya Usmar Ismail, Tiga Dara (1956), yang mengetengahkan drama keluarga dan percintaan. Ia menontonnya untuk pertama kali pada 2007. Sejak itu, tiap bulan Maret, ia yang menjadi koordinator bioskop di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, menyelenggarakan festival bertajuk Sejarah adalah Sekarang dan memutar film tersebut. Meski kesal film favoritnya sudah dalam keadaan memprihatinkan, ia tidak menyerah, “Setelah saya telusuri, rupanya ada ilmu tersendiri untuk merestorasi film.”
Pada 2011, Lisa berangkat ke Belanda dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar di jurusan Preservation and Presentation of the Moving Image, University of Amsterdam.
“Antara tahun 2011 dan 2012, saat saya mulai kuliah di sana, Yayasan Pusat Film Indonesia mengirim Tiga Dara ke Belanda untuk direstorasi. Yayasan ini berdiri sebelum saya meninggalkan Indonesia. Saya turut mendirikannya. Orlow Seunke, salah seorang pendiri yang aktif, mengupayakan restorasi itu,” kenangnya.
Namun, perubahan drastis terjadi di Belanda. Politikus beraliran kanan Geert Wilders memimpin parlemen. Ia memangkas anggaran institusi kebudayaan secara besar-besar, sehingga Nederlands Film Museum, sekarang bernama Eye Institute, yang menerima Tiga Dara tak dapat meneruskan proyek restorasi. Krisis ekonomi mulai melanda Belanda, yang sudah menggerogoti Eropa dan Amerika Serikat sejak 2008. Anggaran kebudayaan dianggap Wilders tidak penting, lalu menjadikannya sasaran empuk pengetatan biaya negara.
Tak berapa lama setelah kabar sedih itu, ia menengok proses restorasi film Lewat Djam Malam (1954), karya lain Usmar Ismail, yang tengah berlangsung di L’immagine Ritrovata, laboratorium film di Bologna, Italia. Lewat Djam Malam mengisahkan kekecewaan bekas tentara pejuang pasca proklamasi saat mengetahui praktik korupsi kawan seperjuangannya dulu. Proyek restorasi film itu didanai oleh National Museum of Singapore, yang merupakan proyek sampingan dari proyek utama untuk mempublikasikan katalog film Indonesia yang disusun JB Kristanto. “Dulu dia wartawan Kompas dan sekarang sudah pensiun. Sahabatnya, seorang kritikus film Singapura, tertarik menerjemahkan katalog tersebut ke dalam Bahasa Inggris. Dia ingin saat katalog itu diluncurkan, sebuah film yang menjadi favorit JB Kristanto turut ditayangkan,” tutur Lisa. Proyek ini dulu tak luput dari keterlibatannya. Pada 2010, ia sempat membantu mencari film tersebut dan menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat restorasi.
Akhirnya Lisa memutuskan magang di Bologna, “Dan sempat terpikir untuk membawa Tiga Dara ke sana.”
Dalam proses restorasinya, Lewat Djam Malam turut didukung yayasan film yang didirikan Martin Scorsese, sutradara terkemuka dunia asal Italia. Pada 2012, Lewat Djam Malam menjadi film pembuka Festival Film Cannes untuk kategori klasik. Persepsi publik terkena imbas. “Orang mulai melihat proyek itu bergengsi, lalu orang-orang kaya mau memberikan uangnya,” tuturnya.
Selama magang, ia merestorasi film-film dari berbagai negara, “Dari yang umurnya 15 tahun sampai 100 tahun.” Setelah lulus kuliah pada 2013, ia ditawari bekerja di L’immagine Ritrovata .
Lisa tidak menampik bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan tukang, “Tapi tukang yang dibekali pengetahuan ilmiah dan filosofi yang baik.” Ia menjelaskan profesi yang memiliki sejarah panjang ini, “Teknisi arsip atau archiver sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sampai sekarang dan mereka tak luput dari tekanan kepentingan politik yang berbeda-beda. Sebab arsip adalah pusat pemikiran.”
Tiga Dara, film yang mengubah jalan hidupnya, kemudian mengalami perubahan nasib. Pada 2015, film itu akhirnya dibawa ke laboratorium di Bologna. Perusahaan swasta di Indonesia, SA Film, mendanai proyek restorasinya. Lisa senang, “Ternyata saya bisa ikut membantu prosesnya dengan ilmu yang sudah saya miliki.”
Merestorasi adalah upaya untuk memulihkan apa yang hilang atau rusak. Ia bersikap kritis terhadap definisi serta praktik “restorasi” yang membabi-buta, “Tujuannya bukan mencipta sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Tapi ada perusahaan-perusahaan komersial yang cenderung mengartikan restorasi sebagai cara membuat film yang direstorasi itu seperti film yang baru disyuting kemarin. Artinya, tidak ada yang asli lagi. Selain itu, ahistoris.”
Ia anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya seorang diplomat. Ibunya putus kuliah, lalu mendampingi sang suami bertugas dari satu negeri ke negeri lain. Keduanya orang Minang. Mereka dijodohkan. Ia menyebut ayahnya ‘bujang lapuk’, “Mungkin dia terlalu sibuk dengan karier. Usia Ayah lebih tua 20 tahun dari Ibu.” Lisa lahir 41 tahun lalu di Lisabon, Portugal. Pengalaman hidupnya berpindah-pindah bersama keluarga hingga usia 17 tahun membuat ia merasa nilai-nilai hidupnya berasal dari semua tempat yang mereka pernah tinggal. Katanya, “Saya terbiasa hidup di mana manusia itu harus struggle dan independen.”
Film pertama yang ia tonton adalah serial Star Wars: Return of the Jedi. Ia menonton bersama sepupu-sepupunya di sebuah bioskop di Kairo, Mesir, “Mungkin itu tahun 1982 atau 1983.” Tapi itu bukan film yang paling mengesankan Lisa. Film-film yang mengesankannya tak lain dari film-film Indonesia, yang dipinjam sang ayah dari koleksi kedutaan untuk diputar di rumah, seperti Gita Cinta dari SMA dan Nakalnya Anak-Anak.
“Ketika teman-teman saya yang lebih dulu kembali ke Indonesia menonton film Catatan Si Boy, saya panik sekali. Mengapa saya ketinggalan menyaksikan kejadian sepenting itu,” katanya, seraya terbahak.
Ia tiba-tiba tercenung, mengingat semua yang sudah lampau, mencoba menarik garis dari masa silam ke masa kini, “Barangkali upaya saya melestarikan film adalah penebusan terhadap masa-masa yang terlewatkan untuk film, masa-masa yang hilang.” (LC) Foto: Dhany Indrianto.
Author
DEWI INDONESIATRENDING RIGHT THIS VERY SECOND
FOOD & TRAVEL
CASA CUOMO, Simfoni Kuliner Italia di Jakarta