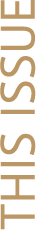Inilah Ritme Kerja Jurnalis Andini Effendi

Ayah dan ibunya pun menekankan bahwa ia harus bekerja dan melanjutkan kuliah. “Tidak usah memikirkan menikah, tapi berkarier dulu,” tutur Andini Effendi ketika dewi berbincang pada satu malam di kantornya, sebelum ia melanjutkan siaran di stasiun televisi swasta nasional. Berayahkan pengusaha dan politikus, sementara ibunya seorang wanita karier, membuat prinsip hidup Andini adalah kerja, kerja, dan kerja.
Ia tertarik pada jurnalisme sejak masih di SMP, berawal dari kebiasaan membaca suratkabar dan majalah yang dipacu didikan sang ibu. Setiap hari ia diharuskan ibunya membaca Koran, “Supaya kalau diajak berdiskusi oleh siapa saja kamu mengerti apa yang dibicarakan,” ujar Andini mengingat perkataan ibunya. “Aku baca Kompas dan Majalah Tempo. Waktu Majalah Tempo dibreidel, aku juga ingat.” Di masa itu pula ia mulai gemar menonton CNN, televisi berita Amerika, dan terinspirasi oleh sosok Paula Zahn, yang memiliki acara tersendiri di televisi tersebut. “Dia siaran di studio, mewawancarai orang-orang, terus meliput di lapangan, lalu dia pulang ke rumah, kembali kepada anak-anaknya di malam hari,” tuturnya kagum. Sejak itu Andini bertekad agar menjadi seorang jurnalis seperti Zahn.
Setamat kuliah di UPH, ia lantas bekerja di Global TV pada 2005. Bidang liputannya mencakup politik, hukum, kriminalitas, dan human interest. Ia hijrah ke ANTV setahun kemudian dan akhirnya menjadi jurnalis Metro TV sejak 2007. Di Metro TV yang berada di bawah naungan Media Group, Andini merasa memperoleh kesempatan belajar lebih banyak dan ditempa berbagai pengalaman.
Pada 2008 ia ditugaskan meliput pembicaraan damai antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis Thailand Selatan di Bogor, yang dijembatani Jusuf Kalla sebagai wakil pemerintah Indonesia saat itu. “Metro TV menjadi media satu-satunya stasiun televisi yang diijinkan meliput,” ujarnya. Maka ia dan timnya kemudian dikirim ke Thailand Selatan. “Kami mewawancarai tokoh oposisi yang kelak menjadi perdana menteri, Abhisit Vejjajiva.” Namun perjuangannya mewawancara tokoh politik tersebut tidaklah mudah. Dalam perjalanan menuju Thailand, cuaca politik berubah. Kudeta militer terjadi di Bangkok, menyebabkan bandara ditutup. Ia dan rekan-rekannya terpaksa naik mobil dari Kuala Lumpur untuk bisa tetap sampai di Bangkok.
Ketika perubahan kekuasaan terjadi di negara-negara Timur Tengah pada awal 2011, ia menjadi segelintir jurnalis dunia yang turut mengabadikannya. Gejolak melanda sejumlah negara di sana, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya. Rezim-rezim lama mulai digulingkan rakyat yang menginginkan pemerintahan yang demokratis. Situasi ini dikenal sebagai “Arab Spring”. Metro TV menyiapkan sebuah tim khusus untuk meliput situasi di Libya. “Terdiri dari laki-laki semua,” tuturnya. Menjelang berangkat, tim ini menemui pemilik dan pemimpin Media Group, Surya Paloh, yang mempertanyakan ketiadaan perempuan dalam tim. Andini pun kemudian dipilih untuk masuk dalam tim tersebut. Penunjukan itu jelas mengagetkannya. Andini baru saja dalam perjalanan pulang dari studio, ketika tiba-tiba ditelepon agar esok hari sudah siap untuk berangkat ke Libya. Liputan akan berlangsung satu minggu. Namun, praktiknya lebih panjang dari itu: tiga bulan.
“Kami masuk lewat Zimbabwe, membuat visa dulu. Mengurus visa butuh waktu satu minggu sendiri. Saat sampai di Libya, suasana sudah tegang. Zona larangan terbang untuk pesawat komersial ke negara itu sudah diberlakukan,” cerita Andini. Hotel tempat ia dan rekan-rekannya menginap pun terletak di muka pangkalan militer Libya.. Konsekuensinya, ia harus mendengar suara ledakan bom dan tembakan tiap malam karena pangkalan militer tadi merupakan sasaran perang.
Andini dan sejumlah wartawan asing menjadi tamu negara itu, sehingga berada di bawah perlindungan pemerintahan Muammar Khadafi. Beberapa kali ia bertemu dengan Khadafi. Beberapa kali pula lelaki ini menyapanya. Khadafi yang sangat mengagumi presiden Soekarno menerima Andini dengan baik. Karena Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ia dan tim Metro TV dapat memasuki tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang sukar dimasuki media asing lain. Pemerintah Libya juga sudah mengatur jadwal kunjungan untuk para jurnalis dari seluruh media asing.
Namun, perang tak pernah luput dari propaganda. Suatu hari ia mendapat kabar bahwa telah terjadi ledakan bom anti pemerintah yang merenggut 100 jiwa. “Wah 100 orang kan banyak banget. Sebagai jurnalis yang sering melakukan liputan kriminalitas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, aku langsung bilang ke tim untuk ke rumah sakit melihat kondisi mayat-mayat itu,” katanya.
Para jurnalis media lain pergi ke lokasi ledakan, tapi Andini dan tim memilih berangkat ke rumah sakit naik taksi. Ternyata tidak ada ambulan yang datang membawa jenazah. Tiga jam kemudian. Lima jam sesudah itu. Lewat dini hari. Tidak ada korban-korban yang sampai. Mereka lantas memeriksa rumah sakit lain. Hasilnya, nihil. Kepada seorang wartawan New York Times yang juga berada di Libya, ia bercerita bahwa kabar tentang jumlah korban pengeboman tidak terbukti.
Atas referensi wartawan itu pula, Andini memperoleh kesempatan diwawancarai untuk seleksi masuk New York University (NYU) di Amerika Serikat. “Menjelang berakhirnya tugas kami di Libya, aku bercerita tentang keinginan untuk masuk ke New York University (NYU), tapi email-ku tidak dibalas NYU,” kata Andini. Sang wartawan New York Times itu kemudian langsung mengirim email ke NYU. Tidak butuh lama, keesokannya Andini langsung dihubungi NYU. Wawancara dilakukan via Skype dan tembak-tembakan terdengar di luar hotel. “Aku ditanya, itu suara apa. Aku bilang, suara tembakan. Wawancara kemudian ditunda, orang NYU tersebut mengatakan bahwa wawancara akan dilanjutkan di lain waktu, asalkan aku bisa selamat dulu dari zona perang,” cerita Andini. Ia akhirnya diterima kuliah di jurusan Resolusi Konflik di universitas idamannya itu.
Meski sempat beberapa kali bertemu muka, Selama di Libya, Andini tidak berhasil mendapat waktu khusus mewawancarai Khadafi yang keburu diungsikan ke tempat yang dirahasiakan akibat situasi yang terus memanas. Kelak Khadafi terbunuh. Sebagian keluarganya menyelamatkan diri ke negara lain. Negara yang berdaulat itu memasuki puncak kekacauan.
Propaganda tak hanya datang dari pemerintah Khadafi yang diserang. Media dan kekuatan musuhnya juga melancarkan propaganda. Andini turut menjadi saksi. “Khadafi dibilang kayak orang gila, selalu bawa tentara perempuan. Dia digambarkan sebagai orang yang agak lunatic. Tapi waktu bertemu, aku melihat dia normal saja. Padahal aku juga sudah berpikiran negatif. Nanti aku diculik lagi. Ternyata dia tidak begitu.”
Hobinya tidak jauh dari kesukaannya bekerja di lapangan, “Traveling,” katanya mantap. Ia gemar mengunjungi negara-negara yang justru bukan tujuan turis, seperti Bolivia dan Equador di Amerika Selatan. Argentina adalah yang paling berkesan. “Berbeda dengan negara Amerika Latin lainnya, benar-benar classy. Dari perjalanan itu aku menemukan dua orang sahabat baru. Orang Bolivia dan orang British-America. Aku mendapatkan warisan persahabatan dari perjalanan itu,” kata Andini.
Di usianya yang sedang prima, prinsip hidup perempuan ini tentu saja masih berkisar seputar pekerjaan. Namun bagi perempuan kelahiran 1982 itu, ia kini juga mulai memperbanyak waktu dengan keluarga. “Setelah pernah tinggal jauh dari orang tua, aku merasa harus tiap minggu ketemu mereka, dan tiap hari perlu mendengar suara mereka. Ia pun juga selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan teman-temannya. Bergaul dan menjalin pertemanan, seperti yang diajarkan ayah ibunya.
Stress relief itu aku peroleh dari keluarga dan teman-temanku.” (LC) Foto: Adithya Wisnu