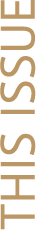Gina S. Noer: Membentuk Narasi yang Baru

“Perempuan, tuh, sudah sering berada di situasi jadi penonton,” kata Gina S. Noer di sela penjelasannya yang berapi-api soal mengapa dunia perfilman butuh lebih banyak praktisi-praktisi perempuan. Apalagi di posisi-posisi strategis seperti produser dan sutradara. Penulis naskah, sutradara, sekaligus produser film itu menyatakan, akibatnya selama ini perempuan terbiasa menerima citra apa yang ditawarkan kepada kita. “Tapi masih sedikit ada yang membuat kita kemudian becermin apa adanya,” lanjut Gina.
Urusan citra perempuan dalam layar memang makin sering diperkarakan beberapa tahun terakhir. Tak bisa dimungkiri representasi perempuan baik di layar lebar maupun di layar televisi merupakan cerminan dari norma-norma patriarkal di masyarakat. Hasilnya sering kali perempuan tampil di layar hanya sebagai sebuah karakter, bukan tokoh yang punya cerita. Ia muncul sebagai proyeksi citra perempuan yang ada di benak laki-laki.
Inilah mengapa menurut Gina diperlukan lebih banyak perempuan di dunia perfilman, untuk memberikan perspektif dan narasi baru akan citra perempuan yang utuh. Ini pula yang ia coba lakukan lewat karya-karyanya. Dunia perfilman menyebutnya sebagai female gaze. Sutradara Jill Soloway dalam monolognya di ajang Toronto International Film Festival 2016 menjelaskan female gaze sebagai bentuk seni visual atau literatur yang dibuat dengan perspektif utuh dan lengkap, tidak melulu berdasar kepada cara pandang laki-laki terhadap dunia dan perempuan sebagai objeknya. Gaze tersebut lantas bisa ditentukan lewat tiga bagian: orang-orang di belakang kamera (termasuk penulis naskah, sutradara, dan produser), hubungannya dengan karakter lain dalam film, serta cara penonton melihat karakter tersebut.
Sepanjang 2019 Gina telah menorehkan namanya di tiga film yang menawarkan kesegaran cerita dan narasi tentang perempuan, ibu, dan keluarga. Ini ia lakukan entah itu sebagai penulis skenario, produser, hingga sutradara. Masing-masing dengan pengalaman dan pelajarannya sendiri. Salah satunya bagaimana ekosistem industri di tempat Gina berkarya sekarang memungkinkannya mengeksplorasi hal itu.
Lewat Bebas, sebagai penulis naskah, ia menghadirkan tokoh-tokoh perempuan muda dan satu laki-laki kemayu serta tokoh-tokoh perempuan usia 40-an dengan segala permasalahan mereka. Hal yang menurutnya sulit dilakukan jika saja film itu tidak digarap sutradara Riri Riza dan diproduseri Mira Lesmana.
Sementara di Keluarga Cemara di mana ia berperan sebagai penulis naskah sekaligus produser, ia memperlihatkan sosok emak yang jauh dari kesan anggun konvensional. “Untuk produser lain mungkin Nirina kurang ayu menjadi sosok Emak. Tapi kan ini ibu zaman sekarang. Beda banget sama Novia Kolopaking dulu. Posisinya pun beda,” jelas Gina. Melalui pendekatan yang berbeda terhadap karakter Emak pula Gina membangun argumen bahwa menjadi keibuan tidak mesti linier dengan tampilan fisik feminin dalam standar masyarakat konvensional.
Eksplorasi karakter yang lebih dalam dan nyata juga ia lakukan dalam film panjang pertama yang ia garap sebagai seorang sutradara, Dua Garis Biru. Ia menghadirkan dua tokoh utamanya sebagai remaja kebanyakan kini, Dara (Adhisty Zara), seorang perempuan remaja penyuka K-Pop dan Bima (Angga Aldi Yunanda) laki-laki yang maskulinitasnya tidak terluka ketika Dara mendandaninya.
Tidak berhenti pada karakterisasi, Gina juga mencoba mengulik peran ibu dengan sudut pandang multidimensi. Alih-alih menghadirkan akhir cerita di mana Dara memilih menjadi ibu ketika anaknya lahir, ia justru meninggalkan buah hatinya itu untuk menimba ilmu di Korea Selatan untuk mengejar mimpinya. Gina memilih untuk memberikan kesempatan kedua bagi protagonisnya. Dan dari sekian banyak hal yang bisa ‘mengganggu’ penonton di film itu, ternyata pilihan akhir cerita itulah yang menuai cukup banyak kritik. Rupanya narasi Gina tersebut semacam menantang konsepsi konvensional tentang ibu dan segala atribut yang melekat padanya.

Dari banyak peran yang ia lakoni sebagai orang belakang layar ia menyatakan paling menikmati posisi sutradara. “Sebagai sutradara itu proses menulisnya terus-menerus,” kata Gina sembari tertawa. Menjadi sutradara menurut Gina adalah sebuah ujian kesabaran kelas dunia. Sebab di situ ia menjadi kepala seluruh proses produksi. Di situ pula ia memegang kendali untuk melakukan eksplorasi. “Bukan cuma untuk bikin film bagus, tapi juga untuk punya momen yang bisa memanusiakan orang lain dalam tim produksi. Ini yang enggak bisa saya lakukan sebagai produser atau penulis skenario,” katanya. Itu semua ia lakukan sembari tetap mempertahankan segala sisi feminitasnya. Kuteks, bantal, dan kipas adalah beberapa hal yang menghiasi area monitornya di set.
Namun, ia pun menyatakan keajekan sikapnya saat menjadi sutradara ia dapat dari peran-peran lain yang ia jajal sebelumnya. “Ini belajar dari pengalaman menggarap Keluarga Cemara ketika saya dan Anggia Kharisma mengikuti saran Mbak Mira Lesmana bahwa menjadi produser itu seperti menjadi ibu,” jelasnya.
Ia pun menyatakan hasilnya berakhir baik. Proses itulah yang kemudian membuatnya memahami dirinya sendiri, menjernihkan visinya, agar bisa lebih optimal dan lebih artikulatif dalam mengarahkan produksi. Hal ini diamini oleh Mira Lesmana saat ditemui di sela peluncuran layanan streaming Go-Play. “Insting saya saat menjadi produser adalah bagaimana caranya mengatur orang-orang kreatif ini, dan ya memang sebenarnya agak keibuan: merangkul, membimbing, dan bisa melahirkan sesuatu yang baik untuk semuanya,” kata Mira lugas dan cepat.
Sementara, pengalamannya berpuluh tahun menjadi penulis skenario mengajarkan Gina untuk terus menerus berefleksi. Baginya setiap penulis mesti tahu alasan mereka. “Buat saya, setiap cerita itu seperti terapi. Jadi ketika dia ada sebagai terapi, kita bisa merefleksikan karakter ini dan mengenali apa yang sama antara dia dan diri kita, sehingga kita bisa menghormati karakter tersebut sebagai manusia yang utuh,” jelas Gina. Naskah Dua Garis Biru misalnya yang ia tulis dan endapkan selama sembilan tahun. Ketika menulisnya pertama kali, ia baru menemukan dua sisi cerita dan belum sreg dengan bagaimana cara karakter-karakternya menyikapi konflik tersebut.
“Sampai kemudian pada 2011, anak kedua saya lahir dengan keadaan bibir sumbing,” kenang Gina. Ia mengakui saat itu ia merasa terpukul karena merasa telah melakukan yang sebaik-baiknya sebagai calon ibu, tetapi anaknya lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Dari pengalamannya berdamai dengan diri sendiri itu ia menemukan apa yang selama ini belum klik dari naskah yang ia tulis: penerimaan. “Apa sih yang membuat orangtua itu menjadi orangtua dan apa sih yang bikin anak itu merasa berarti bagi orangtuanya?” ujarnya.
Semangat reflektif itu yang ia terus bawa di Wahana Kreatif, perusahaan pengembangan konten yang ia rintis bersama sang suami, Salman Aristo. Lewat perusahaan ini, sutradara yang juga menulis film Posesif (2017) ini bercita-cita untuk mendorong banyak orang tak hanya menikmati cerita, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. “Untuk itu para kreator harus paham dengan apa yang terjadi di sekitar mereka dan tahu apa yang mereka refleksikan lewat cerita yang dibuat,” tegas Gina sembari memerhatikan sekali lagi
Gina bukan yang pertama apalagi sineas perempuan satu-satunya yang menyajikan argumen tandingan tentang apa-apa yang dilumrahkan masyarakat. Ada Nia Dinata yang membawakan kita salah satu film terbaik tentang poligami, Berbagi Suami dan film yang bertema LGBT, Arisan!. Atau Mira Lesmana yang secara konsisten mendukung dan memproduseri film dengan narasi cerita yang sederhana tetapi utuh, film Bebas salah satunya. Ada pula Mouly Surya yang bisa membawa tema kekerasan seksual dengan cara yang segar lewat film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.
Mira Lesmana pun menyatakan perempuan memang menjadi salah satu roda penggerak industri perfilman Indonesia di fase mati surinya. “Ada saya, Nan Achnas, Shanty Harmayn, orang-orang yang bersama saya, termasuk Nia Dinata itu di awal-awal kami membuat Kuldesak, Ada Apa dengan Cinta, Petualangan Sherina, Cabaukan, Pasir Berbisik, dan sebagainya,” kata Mira.
Gina menyadari betul film memiliki dampak yang sangat besar bagi penonton. “Sampai Hitler aja bikin film untuk propaganda,” katanya berseloroh. Menonton film memang sebuah pengalaman yang intens, bahkan nyaris spiritual bagi sebagian orang. Film menuntut kita untuk fokus selama berjam-jam mencerap nilai-nilai yang ditawarkan. Di sinilah story argument menjadi penting, “Karena itu yang akan membuka ruang diskusi,” jelas Gina. Tujuannya tentu untuk membentuk dan merefleksikan realitas di sekitar kita. Bukan hanya berdasar kepada cara salah satu gender memandang dunia, tetapi dari citra dunia yang utuh; Yang memungkinkan laki-laki menjadi rapuh dan memberikan ruang ketidaksempurnaan bagi perempuan. (Shuliya Ratanavara).