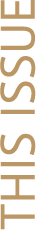Bivitri Susanti, Sosok Inspirasional di tengah Dunia Hukum Indonesia

Ia pernah bercita-cita menjadi pengacara kaya-raya. Namun, situasi menjelang akhir kekuasaan Presiden Soeharto telah mengubah falsafah hidupnya. Pengalaman terlibat dalam aksi dan diskusi ternyata mengawali sebuah titik balik yang membuatnya tak pernah surut lagi, “Saya ingin bekerja untuk lebih banyak orang meski berpenghasilan lebih sedikit,” tutur Bivitri Susanti, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
Bersama beberapa senior yang terdiri dari para pengacara profesional, ia mendirikan PSHK pada 1 Juli 1998. Dulu ia merintis serta mengelola lembaga studi tersebut hanya berdua dengan temannya, tapi sekarang sekitar 30-an orang bekerja di situ. Mereka melakukan berbagai riset dan menerbitkan buku demi mendukung praktik hukum yang adil. Situs hukumonline.com pun diluncurkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan dunia digital.
Tantangan PSHK tidak hanya berasal dari luar. Ketika bergabung dalam Koalisi Anti Politisi Busuk, beberapa pendirinya merasa terusik karena cukup dekat dengan salah satu partai politik. Bibip, begini ia biasa disapa, mengenang ketegangan yang terjadi, “Mereka bilang, ‘kok PSHK ikut sampai sejauh ini’. Biasanya mereka tidak ikut campur. Kami lalu mengingatkan. Sekarang mereka sudah tercerahkan.” Tapi tantangan dari luar tak kalah keras. Ia kecewa terhadap sosok Jaksa Agung pilihan presiden dan tindakan polisi yang mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Baginya, peristiwa-peristiwa tadi menegaskan situasi yang lebih kelam. “Reformasi hukum belum mampu menyentuh oligarki,” tuturnya. Oligarki merujuk pada pemerintahan yang dikendalikan sejumlah orang dari golongan atau kelompok tertentu.
Reformasi sungguh hiruk-pikuk, sehingga membuat apa yang penting nyaris luput dari perhatian. “Tuntutan yang paling lantang adalah reformasi politik. Tidak banyak yang bicara reformasi hukum secara sistematis. Karena itu kami kemudian bergerak di advokasi kebijakan untuk memperbaiki insititusi hukum,” katanya. Namun, upaya tersebut kurang berhasil. Korupsi masih merajalela setelah 17 tahun reformasi. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu tidak dapat dibongkar. “Lebih parah lagi, orang-orang hukum ikut berkonstribusi,” lanjutnya.
Tentu saja, tiada kata menyerah. Bibip dan rekan-rekannya di PSHK sepakat kembali ke hulu, yaitu memperbaiki pendidikan hukum. Mengubah sistem pendidikan di sekolah hukum yang sudah mapan nyaris mustahil dilakukan, sehingga mendirikan sekolah hukum baru terasa memberi harapan. Empat tahun lalu Jentera dicetuskan. Namanya sama dengan jurnal yang diterbitkan PSHK. Jentera berarti roda penggerak. Bibip berharap,“Sekolah ini harus bisa jadi roda penggerak perubahan hukum.”
Sekolah baru membutuhkan waktu untuk meraih kepercayaan publik, sehingga Jentera tidak semata-mata mengandalkan minat lulusan SMA. Ia menerima saran sejumlah teman, “Kalau lulusan SMA, pada akhirnya yang memutuskan bukan anaknya tapi orangtuanya. ‘Anak saya mau masuk ke sekolah apa nih, kok namanya belum pernah dengar’. Jalan keluar kami adalah juga menyasar mahasiswa yang bukan lulusan SMA, yang ingin mengejar gelar kedua.”
Proses perizinan tidak berlangsung cepat. Pertengahan September 2015 kuliah dimulai untuk pertama kali. Selain menerima mahasiswa melalui jalur pendaftaran, Jentera memberi dua jenis beasiswa, yakni beasiswa Jentera dan beasiswa Munir. Beasiswa Munir, khusus untuk aktivis lembaga swadaya masyarakat, sedangkan beasiswa Jentera terbuka untuk umum. Biaya kuliah dan biaya hidup selama di Jakarta ditanggung penuh. Khusus untuk beasiswa Munir, mahasiswa dari Indonesia Timur lebih diprioritaskan dengan tujuan pemerataan pendidikan. Donor atau penyandang dana berasal dari perorangan dan lembaga.
Titik berat kurikulum Jentera pada pemahaman yang kuat terhadap hukum-hukum dasar, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, satuan kredit semester untuk hukum-hukum dasar ini diperbanyak. Ia menegaskan, “Dengan dasar-dasar yang kuat, sarjana hukum yang baik akan bisa menganalisis undang-undang baru apa saja.”
Jentera menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk menyelenggarakan mata kuliah tertentu, seperti dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Pada tahun ke-3 atau tahun ke-4 kuliah, para mahasiswa didorong menjalankan praktik kerja berdasarkan minat. Bibip ingin calon-calon sarjana ini tidak hanya menghafal pasal-pasal, tapi juga menyaksikan serta mengalami penerapan hukum secara langsung. Nilai-nilai, seperti antikorupsi, harus tertanam pada setiap lulusan Jentera, meskipun sikap skeptis justru muncul dari kalangan temannya sendiri. “Ada yang bertanya apakah saya yakin hal itu terwujud. Untuk mendapat jadwal sidang saja harus membayar. Bagaimana caranya untuk menghapus suap sama sekali, katanya. Tapi kalau banyak orang mau susah sedikit, bisa saja datang tiap hari untuk menanyakan jadwal sidang sampai memperolehnya.”
Bibip belajar tentang kejujuran serta tanggung jawab dari ayahnya sendiri. Lelaki itu tidak pernah memberi banyak nasihat, tapi memberi contoh melalui perilaku. Suatu hari seorang teman ayahnya ingin naik pangkat. Ia sengaja membawa peralatan panjat tebing untuk Bibip yang menggemari olah raga tersebut sebagai upaya menyogok sang ayah yang bekerja di biro kepegawaian. Ayahnya segera meminta ia mengembalikan pemberian itu. Bibip terinspirasi menerapkan nilai-nilai di Jentera dengan mengikuti cara ayahnya menanamkan nilai-nilai yang sama terhadap dirinya. “Tidak dengan menceramahi, tapi harus dengan metode yang membuat mahasiswa berpikir bahwa korupsi itu salah,” ujar anak kedua dari tiga bersaudara ini.
Selain mengagumi sosok ayah, ia mengalami momentum penting dalam hidupnya ketika mengenal dekat Daniel S. Lev, seorang profesor ilmu politik Amerika yang menyumbang banyak pemikiran politik dan sejarah hukum tentang Indonesia. “Pak Dan mendorong saya sekolah lagi. Jangan melihat gelarnya, katanya, tapi itu adalah waktu di mana saya bisa berefleksi tentang apa yang bisa saya lakukan, apa yang seharusnya dulu saya lakukan dan apa yang nanti mau saya lakukan,” kisahnya. Pak Dan, guru sekaligus sahabat Bibip, meninggal dunia akibat kanker paru-paru pada 29 Juli 2006 di Seattle, Amerika Serikat.
Tidak hanya itu pesan Pak Dan. “Sebelum meninggal, dia ingin semua bukunya diwariskan ke PSHK, supaya orang-orang Indonesia juga memperoleh manfaat.” Buku-buku itu kini berada di Puri Imperium Office Plaza UG-16, di Jalan Kuningan Madya, Jakarta, menjadi koleksi Daniel S. Lev Law Library. Kami bercakap-cakap di ruang rapat yang terletak di belakang perpustakaan pada sore hari, 29 Juli 2015. Setahun sesudah kepergian Pak Dan, semua bukunya tiba di Jakarta atas bantuan seorang teman Bibip di Seattle.
Akhir tahun ini ia akan meraih gelar doktor dari University of Washington di Seattle. Seharusnya ia mampu menyelesaikan kuliah lebih awal. Tapi beberapa hal terjadi di luar dugaan. Pada 2010, dana beasiswanya dihentikan akibat krisis ekonomi melanda Amerika Serikat. Ia memutuskan pergi ke Hanoi, Vietnam, dan menetap selama dua tahun di sana, ikut sang suami yang bertugas. Bibip pertama kali bertemu Frank Fuelner, lelaki Jerman yang kelak menjadi suaminya, saat menghadiri acara reuni alumni Inggris di Jakarta, “Dia S3-nya di SOAS, University of London. Saya lulusan S2 dari University of Warwick.” Frank bahkan mengenal sejumlah orang Indonesia yang berada di lingkup pergaulan Bibip, “Disertasinya mengenai gerakan mahasiswa 1998.” Setelah makin dekat, mereka merasa cocok berhubungan lebih jauh. Keduanya menikah, lalu di awal 2010 itu Bibip melahirkan putri mereka, Jasmine.
Bibip ternyata menikmati menjadi ibu, “Mungkin itu juga yang membuat saya makin lama lulus.” Ia tertawa. Tiga tahun kemudian, ia kembali ke Amerika Serikat bersama Frank dan Jasmine, karena memperoleh beasiswa untuk riset di Harvard Kennedy School selama satu tahun. Kesempatan ini tidak disia-siakannya. Ia merampungkan disertasi yang tertunda.
“Saya membahas peran para pemain baru dalam wacana negara hukum pasca Orde Baru. Salah satu kesimpulan saya, seperti yang saya katakan tadi, kita gagal melihat adanya oligarki ini.”
Apa yang ingin ia lakukan di masa mendatang? “Karena Jentera masih baru, saya ingin berkonsentrasi di sini dulu,” tukasnya, bersemangat. (LINDA CHRISTANTY) Pengarah gaya: Yudith Kindangen, Fotografer: Rizky Rizahdy
Author
DEWI INDONESIATRENDING RIGHT THIS VERY SECOND
FOOD & TRAVEL
CASA CUOMO, Simfoni Kuliner Italia di Jakarta